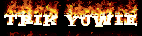Klas-Klas Masyarakat Diperlukan Dan Berlebihan
Friedrich Engels
The Labour Standard - London, Agustus 1881
Telah sering dipertanyakan, hingga seberapa jauh berbagai klas masyarakat itu berguna atau bahkan diperlukan? Dan dengan sendirinya jawabannya berbeda untuk setiap kurun sejarah yang dipersoalkan. Tak disangsikan lagi telah pernah ada masa ketika suatu aristokrasi teritorial merupakan suatu unsur masyarakat yang tak terelakan dan diperlukan. Namun itu, adalah dulu sekali, lama berselang. Ada suatu masa ketika suatu klas kapitalis menengah, suatu burjuasi seperti yang orang Perancis menyebutkannya, lahir dengan keharusan yang sama tidak terelakannya, yang berjuang terhadap aristokrasi teritorial itu, yang mematahkan kekuasaan politiknya, dan pada gilirannya menjadi predominan secara ekonomik dan politik. Tetapi, sejak lahirnya klas-klas, tidak pernah ada suatu zaman di mana masyarakat dapat tanpa suatu klas pekerja. Nama, status sosial dari klas itu telah berubah; para hamba-sahaya telah menggantikan para budak, untuk pada gilirannya digantikan oleh orang pekerja bebas-bebas dari perhambaan tetapi juga bebas dari semua pemilikan keduniaan kecuali tenaga kerjanya sendiri. Tetapi teramat jelas: perubahan apapun yang terjadi pada lapisan-lapisan atas masyarakat, yang tidak-memproduksi (non-producing), masyarakat tidak dapat hidup tanpa suatu klas penghasil/produser. Maka klas inilah yang diperlukan dalam semuas keadaan-walaupun waktunya mesti tiba, ketika ia tidak merupakan suatu klas lagi, ketika ia menjadi (merupakan) seluruh masyarakat.
Nah, keharusan apakah yang ada dewasa ini bagi keberadaan setiap dari ketiga klas ini?
Aristokrasi bertanah, boleh dikatakan, secara ekonomik tidaklah berguna di Inggris, sedang di Irlandia dan Skotlandia ia telah menjadi suatu gangguan positif dikarenakan kecenderungan-kecenderungan depopulatifnya. Mengirim orang menyeberangi samudera atau ke dalam kelaparan, dan menggantikan mereka dengan domba atau kijang-itu saja kegunaan yang dapat diklaim oleh para tuan-tanah Irlandia dan Skotlandia. Coba biarkan persaingan makanan sayur-sayuran dan hewani Amerika berkembang lebih maju lagi, dan kaum aristokrasi bertanah Inggris akan melakukan hal yang sama, paling tidak mereka yang mampu berbuat begitu, karena mempunyai estate-estate (tanah berukuran luas) kota sebagai andalannya. Untuk selebihnya, persaingan makanan Amerika akan segera membebaskan kita. Dan ini yang semujur-mujurnya-karena tindak-politik mereka, baik di Majelis Tinggi dan di Majelis Rendah, sungguh suatu gangguan nasional yang paling puncak.
Tetapi, bagaimana dengan klas kapitalis menengah itu, klas yang telah dicerahkan dan liberal, yang membangun imperium kolonial Inggris dan yang memantapkan kemerdekaan Inggris? Klas yang telah mereformasi parlemen di tahun 1831, membatalkan Undang-undang Gandum dan menurunkan pajak demi pajak? Klas yang menciptakan dan masih mengarahkan manufaktur-manufaktur raksasa, angkatan laut perdagangan yang luar-biasa besarnya, dan sistem perkereta-apian Inggris yang terus meluas? Jelaslah klas itu setidak-tidaknya adalah sama diperlukan seperti klas pekerja yang dikendalikan dan dipimpinnya dari kemajuan ke kemajuan.
Memang, fungsi ekonomik klas menengah kapitalis itu adalah menciptakan sistem modern manufaktur dengan tenaga (mesin) uap dan komunikasi bertenaga uap, dan menghancurkan setiap hambatan ekonomik dan politik yang menunda atau menghalangi perkembangan sistem itu. Tidak disangsikan lagi, selama klas menengah kapitalis menjalankan fungsi ini, dalam keadaan-keadaan seperti itu, ia adalah suatu klas yang diperlukan. Tetapi, masihkah keadaannya seperti itu? Adakah ia masih memenuhi fungsi dasar sebagai pengelola dan penuai produksi sosial bagi keuntungan masyarakat seluruhnya? Mari kita periksa.
Kita mulai dengan alat-alat komunikasi. Dan kita dapati telegrafi berada di tangan pemerintah. Perkereta-apian dan sebagian besar kapal-kapal uap samudera dimiliki, bukan oleh kapitalis-kapitalis individual yang mengelola bisnis mereka sendiri, melainkan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perseroan yang bisnisnya dikelola untuk mereka oleh pegawai-pegawai bayaran, oleh pegawai-pegawai yang kedudukannya sepenuh dan selengkapnya adalah sebagai pekerja-pekerja atasan dan yang dibayar lebih baik. Sedangkan yang mengenai para direktur dan pemegang saham, mereka mengetahui bahwa semakin sedikit yang tersebut duluan mencampuri manajemen, dan yang tersebut belakangan dengan supervisi/pemilikan, semakin baiklah itu bagi perseroan tersebut. Suatu pengawasan yang longgar dan cuma resminya saja memang merupakan satu-satunya fungsi yang tersisa bagi para pemilik bisnis itu. Dengan demikian kita melihat bahwa sesungguhnya para pemilik kapitalis perusahaan-perusahaan raksasa ini tidak mempunyai kegiatan lain dalam perusahaan-perusahaan itu kecuali menerima dividen-dividen (pembagian keuntungan) setengah-tahunan. Di sini fungsi sosial para kapitalis telah dialihkan pada pegawai-pegawai yang dibayar dengan upah; sedangkan ia sendiri terus mengantongi, dengan dividen-dividen itu, upah untuk fungsi-fungsi itu, sekalipun ia telah berhenti mengerjakannya.
Tetapi sebuah fungsi lain masih tersisa bagi kaum kapitalis itu, yang telah dipaksa "pensiun" dari manajemen karena luasnya perusahaan-perusahaan raksasa bersangkutan. Dan fungsi ini ialah berspekulasi dengan saham-sahamnya di pasar bursa. Karena tiada sesuatu untuk dikerjakan, maka para "pensiunan" kita itu, atau yang sesungguhnya para kapitalis yang digantikan itu, berjudi sesuka-suka hati mereka di lingkungan gemah-ripah ini. Mereka pergi ke sana dengan niat tegas untuk mengantongi uang yang pura-pura mereka peroleh (sebagai 'upah') sekalipun mereka mengatakan, bahwa asal-muasal segala pemilikan adalah kerja dan simpanan-barangkali memang asal-muasalnya, tetap jelas bukan tujuannya. Betapa munafiknya: dengan kekerasan menutup rumah-rumah judi yang kecil-kecil, sedangkan masyarakat kapitalis kita tidak dapat hidup tanpa sebuah rumah judi raksasa, di mana berjuta-juta demi berjuta-juta diderita sebagai kekalahan dan dimenangkan, menjadi pusat masyarakat itu sendiri! Di sini, sesungguhnya, keberadaan para kapitalis pemegang saham yang "pensiun" itu tidak hanya menjadi berlebihan, melainkan juga suatu gangguan yang tiada terhingga.
Kenyataan yang sebenarnya dalam perkereta-apian dan perkapalan-uap hari demi hari kian menjadi kenyataan pula bagi semua perusahaan manufaktur besar dan perdagangan. "Pengambangan"-mengubah kongsi-kongsi perseorangan besar menjadi perseroan-perseroan terbatas-telah menjadi kenyataan selama lebih dari sepuluh tahun terakhir. Dari pergudangan-pergudangan kota Manchester hingga bengkel-bengkel dan tambang-tambang batubara di Wales dan di Utara dan pabrik-pabrik Lancashire, segala sesuatu sedang atau telah dibuat mengambang. Di seluruh Oldham nyaris tersisa sebuah pabrik katun yang berada di tangan perseorangan; bahkan pedagang eceran semakin digantikan oleh 'toko-toko koperatif,' yang sebagian terbesarnya hanyalah koperasi dalam nama belaka-tetapi mengenai ini kita tunda untuk lain kali. Demikianlah telah kita melihat bahwa oleh perkembangan sistem produksi kapitalis itu sendiri, kaum kapitalis digantikan secara sama seperti pemintal-tangan. Tetapi dengan perbedaan, bahwa pemintal-tangan ditakdirkan pelan-pelan mati-kelaparan, dan kapitalis yang digantikan itu dengan kematian pelahan-lahan karena terlampau banyak makan. Dalam hal ini mereka umumnya sama saja: kedua-duanya tidak mengetahui harus bagaimana diri mereka itu.
Maka, inilah hasilnya: perkembangan ekonomik masyarakat aktual kita semakin cenderung berkonsentrasi, mengsosialisasikan produksi ke dalam perusahaan-perusahaan raksasa yang tidak dapat lagi dikelola oleh kaum kapitalis tunggal. Segala omong-kosong mengenai "ketajaman melihat", dan keajaiban-keajaiban yang dihasilkannya, berubah menjadi omong-kosong besar segera setelah suatu perusahaan mencapai suatu ukuran tertentu. Bayangkanlah "ketajaman melihat" Perkereta-apian London dan Barat-laut! Tetapi, yang tidak dapat dikerjakan oleh sang majikan/ahli, pekerja biasa, hamba-hamba perusahaan yang berupah, dapat melakukannya dan itupun dengan berhasil.
Demikianlah, kaum kapitalis tidak dapat lagi mengklaim keuntungan-keuntungan/laba sebagai "upah pengawasan/supervisi," karena ia tidak mengsupervisi apapun. Biarlah selalu kita ingat itu, manakala para pembela modal menggembar-gemborkan kalimat itu.
Tetapi, dalam nomor minggu lalu, telah kita coba buktikan bahwa klas kapitalis juga menjadi tidak mampu mengelola sistem produktif rakasa negeri ini; bahwa di satu pihak mereka telah memperluas produksi sehingga secara berkala membanjiri seluruh pasar dengan produk-produk, dan di lain pihak menjadi semakin tidak mampu mempertahankan diri terhadap persaingan dari luar (negeri). Demikianlah kita mendapati, bahwa kita tidak saja dapat dengan sangat baik mengelola industri-industri besar negeri ini tanpa campur-tangan klas kapitalis , tetapi juga, bahwa campur-tangan mereka itu semakin menjadi gangguan tak-terhingga.
Kembali kita berkata pada mereka, "Mundurlah! Berikan kesempatan kepada klas pekerja."
("Klas-klas Masyarakat - Diperlukan dan Berlebihan," diterbitkan dalam The Labour Standard - London, pada bulan Agustus 1881.)
ooo0ooo
Friedrich Engels
(The Conditions Of The Working-Class In England)
Sebuah kota, seperti London, dimana seseorang telah berjalan berjam-jam dan masih juga belum sampai mendekati batas akhir kota tersebut, tanpa menemui sedikitpun tanda yang akan membuatnya mengambil kesimpulan bahwa sebentar lagi ia akan menjumpai daerah alam terbuka, adalah aneh. Konsentrasi kolosal seperti ini, penumpukan jadi satu dua-setengah juta manusia di satu tempat seperti ini, telah melipatgandakan kekuatan dua-setengah-juta manusia ini sebanyak seratus kali; telah mengangkat London menjadi pusat perdagangan dunia, menciptakan dermaga-dermaga raksasa dan mengumpulkan ribuan kapal yang terus menerus memenuhi sungai Thames. Saya belum pernah menjumpai pemandangan yang lebih mengesankan daripada pemandangan sungai Thames pada saat kapal-kapal berlayar naik menuju London Bridge. Kumpulan bangunan, dermaga di kedua tepi sungai, terutama mulai Woolwich ke arah hulu, kapal-kapal yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang tepi sungai, yang makin lama makin berdesakan, sampai akhirnya hanya tersisa sebuah jalur sempit di tengah sungai, sebuah jalur dimana ratusan kapal uap melaju dengan kencang saling berkejaran; semua itu begitu megah, begitu mengesankan, sehingga seseorang hampir tidak dapat menguasai diri, hanyut dalam kemegahan Inggris bahkan sebelum ia memijakkan kakinya di tanah Inggris.1)
Akan tetapi, pengorbanan yang telah diberikan untuk semua kemegahan ini segera terlihat jelas. Setelah menyusuri jalan-jalan di ibukota ini selama satu atau dua hari, dengan susah payah mencari jalan di antara putaran arus manusia dan arus kendaraan yang tiada henti, setelah mengunjungi daerah-daerah kumuh kota metropolitan ini, orang akan segera menyadari untuk pertama kalinya bahwa orang-orang london ini telah dipaksa untuk mengorbankan kualitas terbaik dari sifat kemanusiaan mereka, untuk memungkinkan kehadiran semua keajaiban peradaban yang memenuhi kota ini; bahwa seratus kekuatan lain yang tertidur di dalam jiwa mereka terpaksa tidak diaktifkan, telah ditekan, agar sejumlah kecil yang lain dapat dikembangkan secara penuh dan berlipat-ganda karena disatukan dengan kekuatan yang sama dalam diri individu lain. Putaran arus manusia di jalan-jalan itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang memuakkan, sesuatu yang tidak dapat diterima oleh manusia. Ratusan ribu manusia yang berasal dari segala kelas dan tingkatan itu, bukankah mereka semua adalah manusia-manusia dengan kualitas dan kekuatan yang sama, dengan keinginan yang sama untuk bahagia? Dan bukankah mereka, pada akhirnya, harus mencari kebahagiaan dengan cara yang sama, dan menggunakan perangkat yang sama? Namun tetap saja mereka saling berdesakan satu sama lain seolah-olah mereka tidak memiliki kesamaan, tidak saling berhubungan, dan satu-satunya kesepakatan di antara mereka adalah kesepakatan yang tidak terucapkan, yaitu agar masing-masing tetap berada di jalur trotoar masing-masing agar tidak menghambat arus dari arah yang berlawanan, sementara tidak seorangpun di antara mereka pernah berpikir untuk saling menghormati satu sama lain bahkan dengan sebuah lirikan pun. Ketidakacuhan yang brutal ini, pengasingan yang tak berperasaan dari masing-masing orang dalam kepentingannya sendiri-sendiri menjadi semakin menjijikkan dan menyakitkan dengan semakin berdesakannya individu-individu ini dalam sebuah ruang yang terbatas. Dan, betapapun seseorang mungkin menyadari bahwa pengasingan individu ini, pencarian diri yang sempit ini adalah hal prinsip di dalam masyarakat modern di manapun, tak pernah ada di mana pun prinsip ini begitu telanjang tak bermalu, begitu disadari, seperti di sini, di kerumunan kota besar ini. Peleburan manusia menjadi sekedar sebuah kesatuan, masing-masing memiliki prinsip dan tujuan sendiri-sendiri, seperti sekumpulan atom, di sini dijalankan pada titiknya yang paling ekstrim.
Begitu juga, perang sosial, perang antara satu melawan semua, di sini dinyatakan secara terbuka. Persis seperti dikemukakan dalam buku Stirner terbaru, manusia memandang satu sama lain hanya sebagai objek yang memiliki kegunaan; yang satu mengeksploitasi yang lainnya, dan semuanya berakhir dengan penindasan yang lemah oleh yang kuat, dan segelintir orang yang kuat, yakni kaum kapitalis, mengambil segalanya untuk dirinya sendiri, sementara bagi mayoritas yang lemah, orang-orang miskin, yang tinggal hanyalah kehidupan ala kadarnya.
Kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi di London ini terjadi pula di Manchester, Birmingham, Leeds (nama kota-kota di Inggris juga.-Ed.) dan di semua kota-kota besar. Di mana-mana terdapat ketidakpedulian yang biadab dan egoisme keras di satu pihak dan penderitaan tak bernama di lain pihak; di mana-mana terjadi perang sosial, setiap rumah berada dalam keadaan perang, di mana-mana terjadi perampasan timbal balik yang dilindungi oleh hukum, dan semua terjadi tanpa malu-malu dan diakui secara terbuka sehingga orang menjadi ciut di hadapan konsekuensi dari keadaan sosial yang terwujud dengan gamblang di sini, dan hanya dapat bertanya-tanya mengapa seluruh struktur yang gila ini masih saja bertahan.
Karena modal, yakni kontrol langsung maupun tak langsung tehadap alat kehidupan dan produksi, adalah senjata yang digunakan dalam perang sosial ini, maka jelas bahwa semua kerugian dari keadaan ini pasti jatuh ke tangan orang miskin. Tak seorang manusiapun peduli padanya. Sekali terdampar di pusaran, ia harus berjuang sebisa mungkin. Kalau ia beruntung bisa mendapatkan pekerjaan, yakni kalau kaum borjuasi bermaksud memperkaya diri dengan memperalatnya, ia akan diberikan sejumlah upah yang tidak cukup bahkan untuk menyatukan badan dan jiwanya; kalau ia tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, ia boleh mencuri, kalau tidak takut kepada polisi, atau mati kelaparan, yang dalam hal ini polisi dengan senang hati akan bersedia menjamin bahwa ia mati kelaparan dengan cara yang tenang dan tidak mengganggu orang lain. Selama saya tinggal di Inggris, paling tidak dua atau tiga puluh orang mati karena kelaparan dalam keadaan yang sungguh menjijikkan, dan jarang ada kelompok Jury yang memiliki keberanian untuk mengatakan hal yang sebenarnya dalam perkara ini. Meskipun pernyataan para saksi dalam perkara ini sangat jelas dan tidak dapat dibantah lagi, para Jury yang dipilih dari kaum borjuasi, selalu dapat menemukan pintu belakang untuk melarikan diri dari tuduhan menakutkan tersebut: mati karena kelaparan. Kaum borjuasi tidak berani mengemukakan kebenaran dalam perkara-perkara tersebut sebab hal itu akan berarti mengungkapkan kutukan mereka sendiri. Akan tetapi, kematian secara tidak langsung lebih sering terjadi dibandingkan kematian langsung, sebab kekurangan gizi yang kronis telah menimbulkan suatu penyakit fatal, telah menyebabkan kondisi fisik yang sangat lemah yang penyebabnya sebenarnya bisa dihindari, yang kemudian menimbulkan kondisi yang sangat parah dan berakhir dengan kematian. Buruh-buruh Inggris menamakan hal ini "pembunuhan sosial", dan menuduh seluruh masyarakat Inggris telah melestarikan pelaksanaan kejahatan ini. Apakah mereka salah?
Memang betul, hanya beberapa individu saja yang mati kepalaran, namun apakah ada jaminan bagi buruh-buruh ini bahwa giliran mereka tidak akan datang besok? Siapa yang bisa memberi jaminan pekerjaan padanya, siapa yang bisa menjamin hal itu jika tiba-tiba dengan alasan apapun atau tanpa alasan sama sekali tuan atau majikannya memecat dia besok, ia bisa terus menjalani hidupnya bersama keluarga yang bergantung padanya, sampai ia menemukan seseorang lain yang akan "memberinya roti"? Siapa yang bisa menjamin bahwa keinginan untuk bekerja saja sudah cukup untuk memperoleh kerja, bahwa sifat jujur, rajin, hemat dan semua sifat yang dianjurkan oleh kaum borjuasi adalah merupakan jalan baginya menuju kebahagiaan? Tak seorangpun. Ia hanya tahu ia bisa makan hari ini, dan bahwa ia bisa makan atau tidak besok sama sekali tidak tergantung pada dirinya semata. Ia hanya tahu bahwa setiap hembusan angin, setiap tingkah majikannya, atau setiap putaran buruk dari perdagangan bisa melemparkannya kembali ke dalam arus pusaran ganas yang baru saja ditinggalkannya dengan selamat, di mana sangat sulit atau kadang-kadang bahkan tidak mungkin untuk tetap dapat mengangkat kepala di atas air. Ia tahu bahwa walaupun ia saat ini memiliki mata pencaharian hari ini, belum tentu besok ia tetap memilikinya.
Sementara itu, mari kita teruskan penyelidikan yang lebih rinci tentang kedudukan yang telah diberikan kepada kelas tak berpunya oleh perang sosial. Mari kita lihat imbalan yang diberikan masyarakat kepada buruh-buruh dalam bentuk tempat tinggal, sandang, pangan, kehidupan macam apa yang telah diberikan kepada mereka yang memberikan sumbangan paling banyak terhadap jelannya kehidupan masyarakat; dan mula-mula, mari kita pertimbangkan aspek tempat tinggal.
Setiap kota besar memiliki satu atau lebih daerah kumuh, tempat klas buruh tinggal berdesakan. Memang benar, kemiskinan seringkali hidup di gang-gang yang tersembunyi di sisi tembok-tembok istana orang-orang kaya; tapi pada umumnya, sebuah teritori/daerah yang terpisah telah disediakan untuk mereka, di mana setelah jauh dari penglihatan klas-klas yang lebih berbahagia, mereka boleh berjuang demi hidup semampu mereka. Daerah-daerah kumuh ini tersusun hampir seragam di semua kota-kota besar di Inggris, rumah-rumah terburuk yang terletak di daerah-daerah pemukiman terburuk di setiap kota; biasanya berbentuk gubuk-gubuk bertingkat satu atau dua yang berderet panjang, mungkin dengan ruang bawah tanah yang juga dipakai untuk tempat tinggal, dan hampir selalu dibangun secara tidak beraturan. Rumah-rumah yang terdiri dari tiga atau empat ruangan dan sebuah dapur, di seluruh Inggris, kecuali di beberapa bagian di London, merupakan tempat tinggal yang umum bagi kelas pekerja. Jalan-jalannya biasanya tidak beraspal, kasar, kotor, penuh dengan sampah sisa-sisa sayuran dan kotoran binatang, tanpa saluran pembuangan air ataupun got-got dan dipenuhi bau busuk dan genangan air kotor. Selain itu pertukaran udara segar terhalang oleh metode pembuatan bangunan di seluruh daerah tersebut, dan karena begitu banyaknya manusia yang hidup di sini, berdesakan dalam satu ruang sempit, suasana yang tercipta di tempat tinggal buruh-buruh ini dapat kita bayangkan. Lebih jauh lagi, jalan-jalan di sini juga berfungsi sebagai tempat penjemuran pakaian ketika cuaca sedang cerah; tali-tali terpasang melintang dari rumah ke rumah dan penuh dengan gantungan pakaian basah.
Mari kita telusuri lebih jauh beberapa daerah kumuh menurut urutannya. Mula-mula London,2) dan di London lah terletak daerah kumuh St.Giles yang terkenal yang sekarang, akhirnya, akan dilalui oleh beberapa jalan besar. St. Giles terletak di tengah-tengah daerah yang sangat padat di London, dikelilingi oleh jalan raya yang rindang yang merupakan pusat kehidupan santai kota London, berdampingan dengan Jalan Oxford, Trafalgar Square dan The Strand. Daerah ini merupakan kumpulan tidak beraturan dari rumah-rumah berlantai empat, dengan jalan-jalan sempit, berbelok-belok dan kotor, di mana terdapat kehidupan seperti di jalan-jalan utama kota London, kecuali bahwa di sini yang terlihat hanyalah kehidupan manusia klas pekerja. Sebuah pasar sayuran digelar di jalanan, keranjang-keranjang berisi sayuran dan buah-buahan, yang semuanya tentunya sudah jelek dan tidak layak lagi untuk dipakai, makin menghalangi jalan, dan dari sini, selain dari kios-kios penjual ikan, tersebar bau yang sangat menusuk. Rumah-rumah tersebut terisi penuh, dari ruang bawah tanah sampai ke loteng, kotor di dalam maupun di luar, dan begitu jeleknya penampilan daerah ini sehingga dengan memandangnya saja pun sebetulnya manusia enggan untuk tinggal di dalamnya. Tapi semua ini belum apa-apa jika dibandingkan dengan gubuk-buguk di tanah-tanah dan gang-gang sempit yang terletak di antara jalan-jalan, yang hanya dapat dilaui lewat jalan-jalan tertutup yang terletak di antara rumah-rumah, dimana kotoran dan puing-puing yang terserak di sini betul-betul tak tergambarkan. Di sini hampir tidak ada kaca jendela yang masih utuh, sedang semen pada tembok-temboknya sudah luruh, kusen pintu dan jendela longgar dan patah-patah, pintu-pintu terbuat dari potongan papan tua yang disambung jadi satu dengan paku, atau sama sekali tak berpintu di daerah pencuri ini, sebab pintu hampir-hampir tidak diperlukan sebab tidak ada lagi yang bisa dicuri dari rumah ini. Tumpukan sampah dan debu berserakan di segala arah, dan cairan kotor yang dibung keluar dari pintu-pintu mengumpul jadi satu dalam genangan berbau busuk. Di sini hidup orang-orang yang paling miskin dari kaum miskin, buruh-buruh yang memperoleh upah terendah bersama pencuri-pencuri dan korban-korban pelacuran berdesakan jadi satu, yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Irlandia, atau keturunan Irlandia, dan mereka yang belum tenggelam dalam kolam pusaran kerusakan moral yang melingkupi mereka, dari hari ke hari semakin dalam terbenam, dari hari ke hari semakin kehilangan kekuatan mereka untuk menolak pengaruh kelaparan, sampah dan lingkungan jahat yang merusak jiwa.
Namun St. Giles bukanlah satu-satunya daerah kumuh di London. Di antara jalinan raksana jalan-jalan raya, terdapat ratusan dan bahkan ribuan gang dan petak-petak tanah yang diisi dengan rumah-rumah yang terlalu jelek untuk ditinggali oleh siapapun yang masih dapat mengeluarkan uang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak untuk manusia. Di dekat rumah-rumah megah orang-orang kaya, tempat yang mengenaskan yang merupakan cerminan dari kemiskinan yang paling pahit masih sering ditemukan. Begitulah, beberapa waktu yang lalu, dalam sebuah pemeriksaan oleh petugas pencatat kematian, sebuah daerah yang dekat dengan Portman Square, salah satu daerah terhormat, disebutkan sebagai daerah tempat tinggal dari "kumpulan orang-orang Irlandia yang dirusak jiwanya oleh kemiskinan dan sampah." Demikian pula, dapat kita lihat di jalan-jalan seperti Long Acre, dsb., yang walaupun tidak gemerlapan tapi merupakan daerah-daerah yang "agak terhormat", sejumlah besar gubuk-gubuk bawah tanah yang dari dalamnya bermunculan anak-anak yang tampak kurus dan lemah serta perempuan-perempuan kumal menikmati cahaya matahari. Persis di sebelah Drury Lane Theatre, yang merupakan tater terbesar kedua di london, terletak beberapa jalan yang terburuk di seluruh kota metropolis tsb, yakni Charles Street, King street dan Park Street, dimana terdapat rumah-rumah yang dari ruang bawah tanah hingga langit-langitnya melulu dihuni oleh keluarga miskin. Di daerah paroki St. John dan St. Margareth di tahun 1840, menurut Journal of the Statistical Society, 5.366 keluarga buruh hidup dalam 5.294 "tempat tinggal" (kalaupun bisa dikatakan begitu); laki-laki, perempuan dan anak-anak yang terdampar bersama tanpa perbedaan umur maupun jenis kelamin, terdiri dari 26.830 orang, dan dari jumlah keluarga ini, tiga perempatnya hanya mempunyai satu ruangan saja. Di daerah paroki kaum Aristokrat St. George di Hanover Square, hidup 6.000 orang dalam kondisi yang sama, dan di sini pula, lebih dari duapertiga di antaranya berdesakan dengan tingkat kepadatan satu keluarga dalam satu ruangan. Dan bayangkan bagaimana kemiskinan orang-orang malang ini, yang di antaranya terdapat apara maling yang tidak tahu lagi apa yang akan mereka curi, masih dieksploitasi lagi oleh kelas pemilik tanah dengan cara-cara yang sah menurut hukum! Tempat-tempat tinggal sewaan dengan kondisi sangat buruk di Drury Lane, yang sudah disebutkan di atas, menghasilkan uang sewa sbb: dua ruang bawah tanah, 3 shilling; satu ruang di lantai dasar, 4 shilling; lantai dua, 4 shilling. 6 dime; lantai tiga, 4 shilling; ruang loteng, 3 shilling, untuk seminggu. Dengan demikian para penghuni Charles Street yang kelaparan ini saja setiap tahun mengeluarkan uang untuk sewa rumah sebesar 2.000 poundsterling, dan ke-5.366 keluarga di Westminster yang telah disebutkan di atas membayar uang sewa setiap tahun sebesar 40.000 poundsterling.
Distrik paling luas terletak di sebelah timur Menara london di Whitechapel dan Bethnal Green, tempat tinggal umat gereja buruh terbesar di London. Coba kita simak ceramah Pendeta St. Phillips, Mr. G. Alsthon, tentang keadaan parokinya. Ia katakan:
"Di paroki ini terdapat 1.400 rumah yang dihuni oleh 2.795 keluarga, atau kira-kira 12.000 orang. Ruang yang dihuni oleh begitu banyak penduduk ini luas tanahnya hanya 400 m2, dan di tempat yang penuh sesak seperti ini, tidak heran bila kita menjumpai seorang pria, istrinya, dengan empat atau lima anaknya, dan terkadang, keempat kakek-nenek, tinggal bersama dalam satu ruangan berukuran 4 m2, dimana mereka makan, tidur, dan bekerja. Saya yakin sebelum Uskup London menghimbau seluruh penduduk london untuk memperhatikan paroki paling miskin ini, orang-orang yang tinggal di daerah West End sama sekali tidak pernah mendengar hal ini, sama seperti mereka tidak pernah mendengar tentang kehidupan suku-suku primitif di Australia atau Pulau-Pulau laut Selatan. Dan apabila kita mencari tahu tentang kemalangan ini, melalui pengamatan pribadi, akan kita temukan ketidakberdayaan dan kesengsaraan yang demikian memilukan hingga kita sebagai sebuah bangsa seharusnya malu bahwa keadaan seperti ini sampai terjadi. Saya pernah mengepalai gereja di dekat Huddersfield selama tiga tahun yaitu semasa keadaan sedang buruk-buruknya, tapi sejak saat itu belum pernah saya temukan ketidakberdayaan total orang miskin seperti di Bethnal Green. Tak satupun kepala keluarga dari sepuluh kelularga yang ada yang mempunyai pakaian lain selain pakaian kerjanya, dan itu pun sudah sangat kusam dan compang-camping; kebanyakan bahkan tidak memiliki penutup tubuh selain potongan kain tersebut, dan tidak pula mempunyai tempat tidur selain setumpukan jerami dan serutan kayu."
Deskripsi di atas memberikan gambaran tentang bagian dalam dari gubuk-gubuk ini. Tapi mari kita ikuti dulu pejabat-pejabat Inggris, yang sekali-sekali tersasar ke sini, ke salah satu atau dua rumah buruh-buruh di sini.
Pada satu kesempatan pemeriksaan mayat Ann Galway, 45 th. yang diadakan tanggal 14 November 1843 oleh Mr. Carter, petugas kematian dari Surrey, surat-surat kabar menulis rincian berikut ini tentang almarhumah: Ia selama ini tinggal di White lion Court no. 3, Bermondsey Street, London, bersama seorang suami dan anak lelakinya yang berumur 19 tahun dalam sebuah ruangan kecil yang tidak terisi tempat tidur ataupun perkakas lainnya. Ia terbaring kaku di samping anaknya di atas setumpukan bulu ayam yang berserakan menutupi tubuhnya yang hampir telanjang, karena ketiadaan selimut ataupun kain lain yang dapat dipakai untuk menyelimutinya. Bulu-bulu ayam tersebut melekat begitu kuatnya di tubuh mayat sehingga dokter baru bisa melakukan pemeriksaan setelah mayatnya dibersihkan, dan kemudian baru terlihat tubuh yang kurus karena kelaparan dan luka-luka karena gigitan kutu. Sebagian lantai di ruangan ini sudah lepas-lepas dan salah satu lubang yang tercipta di sudut ruangan digunakan sebagai WC oleh keluarga ini.
Pada hari Senin, 15 Januari 1844, dua anak laki-laki diseret ke hadapan hakim polisi karena, didorong oleh kondisi kelaparan, telah mencuri dan langsung mnyantap sepotong kaki sapi setengah matang dari sebuah toko. Sang hakim merasa terpanggil untuk menyelidiki lebih jauh kasus tersebut, dan tak lama kemudian menerima laporan dari seorang polisi sbb: ibu dari kedua anak tersebut adalah janda seorang bekas tentara, yang kemudian menjadi polisi, dan telah hidup dalam kemiskinan sejak kematian suaminya, dalam upaya menghidupi kesembilan anaknya. Ia tinggal di Pool's Place no. 2, Quaker Court, Spitalfields, dalam keadaan sangat miskin. Pada waktu polisi tersebut mendatanginya, ia menemukan ibu itu secara harfiah berdesakan dengan enam orang anaknya dalam sebuah ruang belakang yang sempit, tanpa perkakas yang berarti kecuali dua buah kursi beralas anyaman rotan yang tempat duduknya sudah hilang, sebuah meja kecil yang dua kakinya sudah patah, sebuah cangkir yang retak dan sebuah piring kecil. Di perapian, tak sepercik api pun terlihat, dan di salah satu sudut ruangan tertumpuk kain-kain tua yang hanya cukup untuk membuat sebuah rok wanita, yang digunakan sebagai tempat tidur oleh keluarga tersebut. Untuk pakaian tidur, mereka cuma punya baju compang-camping yang mereka pakai setiap hari. Perempuan malang tersebut mengatakan bahwa ia terpaksa menjual tempat tidurnya setahun sebelumnya untuk dapat membeli makanan. Kasur dan selimut ia gadaikan di toko makanan. Pendeknya, semua barang terpaksa dilego demi sesuap nasi. Pak Hakim kemudian memerintahkan agar keluarga perempuan ini menerima jatah ransum makanan bagi orang miskin dalam jumlah cukup besar.
Pada Februari 1844, Theresa Bishop, seorang janda berusia 60 tahun diusulkan, bersama anak perempuannya berusia 26 th yang sedang sakit, untuk diperhatikan oleh Pak Hakim di Marlborough Street. Ia tinggal di Brown Street no. 5, Grosvenor Square, dalam sebuah ruang belakang yang tidak lebih besar dari sebuah lemari, tanpa sepotong perkakas rumahpun. Di satu sudut terserak beberapa potong kain tua yang menjadi tempat tidur bagi keduanya, dan sebuah bufet kecil yang berfungsi sebagai meja sekaligus kursi. Sang Ibu memperoleh sedikit penghasilan dari bekerja membersihkan rumah orang. Pemilik rumah mengatakan bahwa mereka sudah hidup seperti itu sejak Mei 1843, sudah mulai sedikit demi sedikit menual atau menggadaikan semua yang mereka miliki, dan tetap belum mampu membayar sewa kamar. Pak Hakim kemudian memerintahkan pemberian uang sebanyak satu Poundsterling dari dana sosial untuk orang miskin.
Saya sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa semua klas pekerja London hidup dalam kekurangan seperti ketiga keluarga yang disebutkan di atas. Saya tahu betul bahwa sepuluh keluarga hidup dengan baik sementara satu keluarga lain betul-betul terinjak-injak di bawah kaki masyarakat; tapi saya ingin menegaskan bahwa ribuan rakyat pekerja yang sangat berharga-jauh lebih berharga dan lebih patut dihormati daripada semua orang kaya di London-sungguh-sungguh berada dalam keadaan yang tidak semestinya dialami oleh manusia; dan bahwa setiap kaum proletar, setiap orang tanpa kecuali, mengalami nasib yang terjadi bukan karena kesalahan mereka sendiri, meskipun segala daya upaya telah mereka kerahkan bagi sebuah kehidupan yang layak.
Meskipun begitu, mereka yang dapat menemukan tempat berteduh, walaupun seadanya, sudah termasuk beruntung; beruntung dibandingkan dengan mereka yang samasekali tidak punya tempat tinggal. Di London, 50.000 manusia terbangun dari tidur setiap pagi tanpa tahu dimana mereka akan membaringkan tubuh lelah mereka malam berikutnya. Yang paling beruntung dari kumpulan manusia ini, yakni mereka yang berhasil menyimpan satu atau dua pennies hingga malam harinya, masuk ke tempat-tempat penampungan/penginapan, seperti yang banyak terdapat di setiap kota besar, untuk memperoleh tempat tidur. Tapi tempat tidur yang sungguh menyedihkan! Rumah-rumah penginapan ini dipenuhi tempat tidur dari ruang bawah tanah sampai ke loteng; empat, lima, enam tempat tidur dalam satu ruangan; sebanyak yang bisa didesakkan ke dalam satu kamar. Ke atas setiap tempat tidur, empat, lima, enam manusia ditumpuk jadi satu, sebanyak yang bisa ditumpukkan, sehat ataupun sakit, tua atau muda, mabuk atau sadar, laki-laki dan perempuan, siapa saja yang datang lebih dahulu, tanpa ada perbedaan. Lalu pasti terjadi pertengkaran, pukulan, luka, jika kawan setempat tidur ini sepakat, sesuatu yang lebih buruk lagi; pencurian diatur, dan banyak hal dilakukan, hal-hal yang tidak dapat tergambarkan oleh bahasa kita, yang telah berkembang menjadi lebih manusiawi dibandingkan perbuatan-perbuatan kita. Dan bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu membayar tempat bermalam seperti itu? Mereka tidur di mana saja mereka temukan tempat kosong, di lorong-lorong, di emper-emper toko, di sudut-sudut jalan dimana polisi dan bahkan pemilik tanah pun tidak tega membangunkan mereka. Beberapa orang berhasil mencapai tempat-tempat penampungan yang dikelola, di beberapa tempat, oleh badan-badan amal swasta, sementara yang lain tidur di bangku-bangku taman tidak jauh dari jendela Ratu Victoria. Coba kita simak tulisan di London Times di bawah ini:
"Terungkap dari laiporan jalannya persidangan di Pengadilan Polisi Marlborough Street yang dimuat dalam kolom kami terbitan kemarin, bahwa rata-rata terdapat lima puluh manusia segala usia, yang berdesakan di taman setiap malam, karena tidak memiliki tempat berteduh lain selain yang diberikan oleh pohon-pohon dan beberapa ceruk yang tercipta di dinding kanal. Dari jumlah ini, kebanyakan adalah gadis-gadis muda yang telah terbujuk oleh tentara-tentara untuk meninggalkan desa mereka dan kemudian ditinggalkan luntang-lantung dengan segala ketidakberdayaan dalam kemiskinan tanpa kawan dan buruknya kejahatan di usia dini.
"Ini sungguh mengerikan! Kemiskinan ada di mana-mana. Kepapaan akan menjalar dan mendirikan kerajaannya yang mengerikan di jantung sebuah kota yang megah dan mewah. Di antara ribuan jalan-jalan sempit dan gang-gang kecil sebuah kota metropolitan yang padat penduduk, saya khawatir, akan selalu ada banyak penderitaan-banyak pemandangan yang menyakitkan mata-banyak mengintai tanpa terlihat.
"Tapi bahwa di tengah daerah kaya, kesenangan dan mode, di dekat kemegahan St. James, tidak jauh dari keindahan istana Bayswater, diapit oleh daerah pemukiman aristokrat yang lama dan baru, di sebuah distrik dimana peremajaan desain modern yang dilakukan dengan sangat hati-hati telah menolak untuk membuat satu bangunan perumahan untuk kaum miskin; yang, dengan demikian, tampak ditujukan hanya bagi kenikmatan kekayaan, bahwa di sini kemiskinan, dan kelaparan, dan penyakit, dan kejahatan justru mengendap-endap dengan segala kengerian yang ditimbulkannya, melahap tubuh demi tubuh, jiwa demi jiwa!
"Sungguh suatu keadaan yang mengerikan! Kenikmatan sebagai sesuatu yang absolut, dimana kenyamanan tubuh, kesenangan intelektual, atau kesenangan keindraan yang lebuh lugu lainnya menjadi pusat keinginan manusia, disandingkan dengan kesengsaraan yang paling menyakitkan! Kekayaan, dari ruang "saloon"nya yang terang benderang, mentertawakan-dengan tawa yang tak berperasaan dan kurang ajar-luka luka kemiskinan yang tidak dikenalnya! Kesenangan, dengan kejam tapi tanpa disadari mengejek rasa sakit yang mengerang di bawah sana! Semua hal yang bertentangan saling mengejek-segala yang bertentangan, kecuali kejahatan yang menggoda dan kejahatan yang tergoda!
"Tapi biarlah manusia mengingat satu hal-yaitu bahwa di tengah daerah pemukiman paling anggun di kota terkaya di bumi Tuhan ini, bisa ditemukan, dari malam ke malam, dari musim dingin ke musim dingin berikutnya, perempuan-perempuan-yang muda dalam usia namun tua dalam dosa dan penderitaan-dicampakkan dari masyarakat - MEMBUSUK KARENA KELAPARAN, KOTORAN, DAN PENYAKIT. Biarlah mereka mngingat hal ini, dan belajar darinya bukan untuk berteori melinkan untuk melakukan sesuatu. Tuhan tahu bahwa banyak sekali yang harus dilakukan dewasa ini."3)
Telah saya sebutkan di atas tentang adanya tempat bermalam bagi para tunawisma. bagaimana penuh sesaknya tempat-tempat tersebut bisa dilihat dari dua contoh berikut. Sebuah tempat penampungan bagi tunawisma yang baru dibangun di Upper Ogle Street yang berkapasitas 300 orang per malam, sejak dibuka pada 27 Januari s/d 17 maret 1844, telah menampung 2.740 orang untuk satu malam atau lebih; dan meskipun cuaca sudah lebih baik, jumlah pendaftar di tempat penampungan ini maupun di Whitecross Street dan Wapping meningkat pesat serta sejumlah besar tunawisma terpaksa ditolak setiap malam akiba kurangnya jumlah ruangan yang tersedia. Di tempat penampungan lain, di Central Asylum di Playhouse Yard, 460 tempat tidur disediakan setiap malam selama tiga bulan pertama tahun 1844, 6.681 orang diberi naungan dan 96.141 porsi roti dibagikan. Namun komite pengurusnya menyatakan bahwa lembaga ini baru bisa memenuhi tekanan orang-orang miskin tersebut sampai tingkat yang terbatas setelah Eastern Asylum juga dibuka.
Mari kita tinggalkan London dan mengamati kota-kota besar lain di ketiga kerajaan sesuai urutannya. Pertama mari kita lihat Dublin, sebuah kota yang bila didekati dari laut tampak mempesona, sama seperti London tampak mengesankan. Teluk Dublin merupakan yang terindah di seluruh Kerajaan Kepulauan Inggris, dan orang-orang Irlandia bahkan membandingkannya dengan keindahan Teluk Napoli. Kotanya pun memiliki pesona yang besar, dan daerah-daerah aristokratnya pun lebih baik dan ditata dengan lebih berselera dibandingkan di kota-kota lain di Inggris. Akan tetapi bila dibandingkan lebih jauh, daerah-daerah miskin di Dublin merupakan yang paling mengerikan dan menjijikkan untuk dilihat di seluruh dunia. Memang benar, watak Irlandia, yang, dalam keadaan tertentu, hanya bisa merasa nyaman dalam kekotoran, terlihat di sini; akan tetapi, karena kita bisa menemukan beribu-ribu orang Irlandia di setiap kota besar di Inggris dan Skotlandia, dan karena setiap penduduk miskin pasti secara perlahan tenggelam ke dalam kekotoran yang sama, keadaan Dublin yang menyedihkan ini bukanlah sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang aneh dan khas yang hanya ada di Dublin, melainkan sesuatu yang biasa terdapat di semua kota besar. Daerah miskin di Dublin sungguh sangat luas, dan kekumuhannya, keadaan rumah-rumah yang tidak layak huni dan jalan-jalan yang tidak terurus, sungguh tak tergambarkan. Sebuah gambaran tentang bagaimana orang-orang miskin di sini ditempatkan berdesak-desakan dapat dilihat dari kenyataan bahwa, pada tahun 1817, menurut laporan Inspektur Workhouses,4) 1.318 jiwa hidup dalam 52 rumah dengan 390 kamar di Barral Street, dan 1.997 jiwa dalam 71 rumah dengan 393 kamar di sekitar Church street; bahwa:
"Di sini and jalan-jalan lain di sekitarnya terdapat jalan-jalan kecil dan gang-gang; kebanyakan ruang bawah tanahnya hanya menrima cahaya dari pintu, sementara di banyak tempat para penghuninya tidup di atas lantai, meskipun kebanyakan dari mereka paling tidak mempunyai mempunyai tempat tidur (tanpa kasur); Nicholson's Court, misalnya berisi dua puluh delapan ruang kecil yang mengenaskan dengan 151 manusia yang berada dalam keadaan sangat kekurangan, sebab hanya ada dua tempat tidur and dua buah selimut di tempat itu."
Kemiskinan di Dublin begitu meluas, sehingga satu-satunya lembaga amal, the Mendicity Association, memberikan bantuan kepada 2.500 orang atau satu persen dari keseluruhan penduduk setiap harinya, menerima mereka dan memberi makan di siang hari dan menyuruh mereka pergi malam harinya.
Dr. Alison menggambarkan sebuah situasi yang sama di Edinburgh, yang keadaan kotanya yang baik telah menyebabkannya menerima julukan Atena Modern, dan yang daerah aristokratnya di New Town sangat kontras dengan kesengaraan kaum miskin di Old Town. Alison menegaskan bahwa keadaan kaum miskin di Scotlandia, terutama di Edinburgh dan Glasgow, jauh lebih buruk dibandingkan di wilayah lain di ketiga kerajaan, dan bahwa yang paling miskin bukanlah orang Irlandia melainkan orang-orang Scotlandia. Seorang pendeta dari the Old Church of Edinburgh, Dr. Lee, memberi pengakuan pada tahun 1836, di hadapan Komisi Pengajaran Agama, bahwa:
"belum pernah ia menyaksikan penderitaan seperti yang ia temukan di dalam parokinya, dimana orang hidup tanpa memiliki sepotong perkakas rumah pun, bahkan tanpa memiliki apa-apa, dimana dua pasang suami istri harus hidup bersama di dalam satu ruangan. Dalam satu hari saja ia sudah mengunjungi tujuh buah rumah yang di dalamnya tidak terdapat tempat tidur, di beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki tumpukan jerami untuk tempat tidur. Orang-orang tua berumur delapan puluhan tidur di atas lantai kayu, dan hampir semuanya tidur dengan memakai pakaian yang mereka gunakan di siang harinya. Pada sebuah ruang bawah tanah ia menemukan dua keluarga yang bersala dari sebuah distrik desa Skotlandia; tak lama setelah mereka tergusur ke kota, dua di antara anak-anak mereka telah meninggal, dan yang ketiga sedang sekarat pada saat ia berkunjung. Masing-masing keluarga memiliki setumpuk jerami kotor di satu sudut; selain kedua keluarga itu, ruang bawah tanah ini juga menjadi tempat naungan seekor keledai, dan keadaan ruang tersebut begitu gelap sehingga hampir tidak mungkin membedakan satu orang dengan orang lain bahkan di siang hari. Dr. Lee menyatakan bahwa keadaan tersebut begitu memilukan sehingga dapat membuat hati yang paling keras pun berdarah menyaksikan penderitaan demikian dapat terjadi di sebuah negeri seperti Skotlandia."
Dalam Medical and Surgical Journal yang terbit di Edinburgh, Dr. Hennan melaporkan suatu keadaan serupa. Dari Laporan Parlemen,5) jelas terlihat bahwa tempat pemukiman kaum miskin di Edinburgh sangat kotor, seperti yang biasa terjadi pada situasi demikian. Di kaki tempat tidur ayam-ayam berkokoki di waktu fajar, anjing-anjing dan kuda berbagi tempat dengan manusia, dan akibat yang wajar timbul dari keadaan ini adalah udara yang selalu bau busuk, dan lingkungan yang dipenuhi kotoran dan kumpulan kutu busuk dan kutu-kutu binatang. Pembangunan yang sedang berjalan di Edinburgh mempertahankan kondisi yang kejam dan memalukan ini sejauh mungkin. Old Town dibangun di kedua lereng sebuah bukit yang di puncaknya terbentang jalan utama High Street. Keluar dari High Street, akan tampak puluhan gang-gang sempit dan berbelok-belok yang disebut wynds karena banyaknya belokan di jalan ini, dan di kelokan-kelokan inilah terletak distrik proletar di kota ini. Rumah-rumah di kota-kota Skotlandia pada umumnya adalah bangunan-bangunan yang terdiri dari lima atau enam lantai, seperti di Paris, dan berbeda dengan rumah-rumah di Inggris, di mana setiap keluarga, sedapat mungkin memiliki rumah sendiri. Penumpukan manusia di dalam satu areal terbatas menjadi semakin intensif di sini.
"Jalan-jalan di sini," demikian dilaporkan sebuah majalah Inggris dalam sebuah artikel tentang kondisi sanitasi kaum buruh di kota-kota, "seringkali begitu sempit sehingga seseorang bisa melangkah dari jendela satu rumah ke jendela rumah di depannya, sementara rumah-rumah dibangun begitu tinggi, lantai demi lantai, sehingga cahaya hampir tidak mampu mencapai halaman ataupun gang di antara rumah-rumah itu. Di bagian kota ini tidak terdapat gorong-gorong ataupun selokan, atau bahkan WC yang seharusnya terdapat dalam setiap rumah. Akibatnya, semua sampah dan kotoran dari sekitar 50.000 manusia dibuang ke dalam got-got setiap malam, sehingga meskipun ada penyapuan jalan, sejumlah besar kotoran kering dan bau busuk tercipta di sini, yang tidak hanya mengganggu pandangan dan penciuman, tapi juga sangat membahayakan kesehatan penduduk daerah ini. Apakah kita perlu heran bahwa di tempat seperti ini semua pertimbangan kesehatan, moral, dan bahkan kesopanan yang paling umum sama sekali diabaikan? Sama sekali tidak. Sebaliknya, semua orang yang lebih mengetahui lebih dekat kondisi penduduk di sini akan dengan jujur memberi kesaksian terhadap tingginya tingkat penyebaran penyakit, kesengasaraan dan demoralisasi yang menimpa daerah ini. Rumah-ruamh orang-orang miskin ini umumnya sangat kotor, dan jelas tidak pernah dibersihkan. Pada umumnya rumah-rumah tersebut terdiri dari satu ruangan yang, karena keadaan ventilasi yang sangat buruk, selalu dalam keadaan dingin akibat jendela-jendela yang patah ataupun tidak terpasang dengan baik, kadang-kadang sangat lembab dan sebagian terletak sedikit lebih rendah dari jalan, selalu hampair tanpa perkakas rumah dan sangat tidak menyenangkan, setumpuk jerami seringkali menjadi tempat tidur bagi seluruh keluarga, dimana laki-laki dan perempuan, tua dan muda, tidur dalam kebingungan yang memuakkan. Air hanya bisa diperoleh dari pompa umum, dan kesulitan mendapatkannya dengan sendirinya telah mengakibatkan tersebarnya segala kotoran yang mungkin terjadi."
Di kota-kota besar pelabuhan lainnya, prospek yang terjadi tidak jauh berbeda. Liverpool, dengan segala jenis perdagangan, kekayaan dan kemewahannya memperlakukan buruh-buruhnya dengan kebiadaban yang sama. Seperlima dari keseluruhan jumlah penduduknya, yaitu lebih dari 45.000 manusia, hidup di tempat-tempat pemukiman ruang bawah tanah yang sempit, gelap, lembab dan berventilasi buruk, 7.862 orang di antaranya terdapat di kota-kota. Di samping tempat-tempatpemukiman bawah tanah ini, terdapat pula 2.270 blok-blok kecil (court), lahan-lahan sempit yang di keempat sisinya dibangun rumah-rumah dengan hanya satu jalan masuk yang sempit dan tertutup, yang biasanya sangat kotor dan dihuni sepenuhnya hanya oleh kaum proletar. Tentang tempat-tempat seperti ini, kita akan memperoleh gambaran yang lebih lengkap pada waktu membicarakan daerah Manchester nanti. Di Bristol sendiri, pada suatu kesempatan kunjungan, dari 2.800 keluarga yang dikunjungi, 46% di antaranya masing-masing hanya menempati satu ruangan.
Keadaan yang persis sama juga berlangsung di kota-kota pabrik/industri. Di Nottingham, secara keseluruhan terdapat 11.000 rumah, 7.000 sampai 8.000 di antaranya dibangun rapat saling berbelakangan dengan dinding belakang menyatu sehingga tidak mungkin ada ventilasi, sementara satu buah WC bisanya disediakan untuk beberapa rumah. Selama penelitian yang dilakukan beberapa waktu kemudian, beberapa deret rumah tampak telah dibangun di atas got-got dangkal yang hanya ditutupi papan-papan lantai dasar. Di Leicester, Derby dan Sheffield, keadaan tidak lebih baik. Mengenai Birmingham, artikel diatas yang dikutip dari Artisan menyatakan:
"Di daerah kota lama, terdapat banyak daerah yang sangat kumuh, kotor dan terabaikan, penuh dengan kolam air kotor dan tumpukan sampah dan kotoran. Blok-blok perumahan sempit (Court) di Birmingham jumlahnya sangat banyak, mencapai dua ribu blok, dan di sini tinggal jumlah terbesar kaum pekerja kota ini. Blok-blok ini biasanya sempit, berlumpur, dengan ventilasi sangat buruk, tidak memiliki saluran pembuangan (gorong-gorong) dan berisi delapan sampai dua puluh rumah, yang, karena dinding belakangnya sangat rapat, biasanya hanya dapat mempunyai ventilasi dari satu arah saja. Di bagian belakang, di dalam blok ini, bisanya terdapat tumpukan sampah atau yang semacamnya, yang kotornya tidak dapat digambarkan di sini. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa blok-blok yang lebih baru dibangun dengan lebih masuk akal dan dipelihara dengan lebih baik, dan bahkan di blok-blok lama, pondok-pondok yang ada tidak terlalu penuh sesak seperti di Manchester dan Liverpool, dimana Birmingham memperlihatkan tingkat kematian yang jauh lebih kecil, bahkan pada waktu terjadinya suatu epidemi, daripada, misalnya, Wolverhampton, Dudle dan Bilston, yang hanya berjarak beberapa mil saja dari kota itu. Pemukiman ruang bawah tanah tidak dikenal di Birmingham, meskipun beberapa ruang bawah tanah disalahgunakan sebagai ruang kerja di beberapa rumah. Rumah-rumah penampungan bagi kaum proletar terdapat gaka banyak di sini, kebanyakan di blok-blok pemukiman (court) di jantung kota. Hampir semuanya terlihat jorok dan berbau, tempat bernaung para pengemis, maling-maling, gelandangan, dan pelacur-pelacur, yang makan, minum, merokok, dan tidur tanpa sedikitpun mengindahkan kenyamanan atau kesopanan dalam suatu atmosfir yang hanya tertanggungkan oleh makhluk-makhluk rendah ini."
Keadaan di Glasgow, dalam banyak hal, serupa dengan keadaan di Edinburgh, dengan jalan-jalan sempit berbelok-belok yang sama, dan rumah-rumah tinggi yang sama. Tentang kota ini, artikel di dalam Artisan menyatakan:
"Klas pekerja di sini merupakan 78% dari jumlah keseluruhan penduduk (sekitar 300.000 orang), dan hidup di bagian kota yang melampaui kepapaan dan kekotoran ceruk paling rendah di St. Giles dan Whitechapel, daerah Liberties di Dublin, serta daerah kelokan Edinburgh. Ada beberapa tempat seperti itu di jantung kota, di bagian selatan Trongate, di sebelah Barat Saltmarket, di Calton dan di ujung High Street, labirin tanah-tanah atau kelokan yang tak ada habis-habisnya, yang hampir di setiap belokan terdapat blok-blok kecil (court) dan gang-gang buntu yang terbentuk oleh rumah-rumah bobrok yang berventilasi buruk, bertingkat tinggi dan hampir tanpa sumber air bersih. Tempat-tempat ini secara harfiah dikerubuti manusia. Setiap lantai menampung tiga sampai empat keluarga, yang barangkali terdiri dari dua puluh jiwa. Dalam beberapa kasus setiap lanatai disewakan sebagai tempat-tempat tidur di malam hari, sehingga lima belas sampai dua puluh orang dijejalkan, satu di atas yang lainnya, saya tidak dapat mengatakan ditampung, dalam satu ruangan. Distrik ini menjadi tempat bernaung anggota masyarakat yang paling miskin, tersingkir, dan tak berharga, dan dapat dianggap sebagai sumber epidemi yang menakutkan yang, dimulai di sini, menyebarkan kehancuran atas Glasgow."
Sekarang mari kita dengar bagaimana J.C. Symons, Komisioner Pemerintah untuk Penyelidikan atas kondisi pengrajin tangan, mengambarkan bagian kota ini: 6)
"Saya sudah pernah melihat kesengsaraan dalam tahapnya yang paling buruk baik di sini maupun di dataran benua (Eropa.-pen.), tapi sampai saya melihat keadaan di Glasgow, saya tidak percaya bahwa begitu banyak kejahatan, penderitaan, dan penyakit dapat hidup di suatu negeri beradab. Di rumah-penginapan di daerah bawah, sepuluh, dua belas, terkadang bahkan dua puluh orang dari kedua jenis kelamin, segala umur dan berbagai tingkat ketelanjangan, tidur tanpa kecuali berdesak-desakan di lantai. Tempat-tempat hunian ini biasanya begitu lembab, jorok dan bobrok, sehingga tak seorangpun ingin menyimpan, bahkan, kudanya di situ."
Dan di tempat lain:
"Kelokan Glasgow dihuni oleh jumlah penduduk yang selalu bervariasi antara 15.00 sampai 30.000 jiwa. Wilayah ini seluruhnya terdiri dari gang-gang sempit dan blok-blok kotak dan di tengah-tengah masing-masing blok terdapat tumpukan kotoran. Meskipun penampilan luar wilayah ini begitu menjijikkan, saya sama sekali tidak siap menyaksikan kesengsaraan dan kejorokan yang terdapat di dalamnya. Di beberapa tempat tidur yang kami kunjungi (Kepala Polisi, Kapten Miller dan Symons) kami dapati selapis penuh manusia terkapar di lantai, seringkali lima belas sampai dua puluh orang, beberapa di antaranya berbaju sedangkan sebagian lagi telanjang, laki-laki dan perempuan tanpa kecuali. Tempat tidur mereka hanyalah setumpukan jerami kusut, dicampur dengan beberapa potong kain perca. Hampir tidak ada perabot rumah, dan satu-satunya tanda bahwa tempat ini layak dihuni oleh manusia hanyalah adanya api yang menyala di perapian. Pencurian dan pelacuran merupakan cara hidup (subsisten) yang utama penduduk di sini. Tak seorangpun yang berusaha membersihkan kandang Augea ini, Pandemonium ini, jalinan kejahatan, kotoran, dan wabah penyakit di pusat kota kedua di kerajaan ini. Penyelidikan yang paling lengkap pun terhadap distrik paling miskin di kota-kota lain tidak pernah mengungkapkan sesuatu yang keadaanya separuh dari keadaan di Glasgow ini, baik dalam intensitas kesehatan moral maupun fisik, atau dalam hal kepadatan penduduknya. Sebagian besar rumah di wilayah ini telah dinyatakan bobrok dan tidak layak huni oleh Pengadilan Perburuhan (the Court of Guild), tapi justru tempat inilah yang paling padat penduduknya, sebab, menurut hukum, siapapun yang tinggal di sini tidak boleh dikenakan uang sewa."
Friedrich Engels
The Labour Standard - London 1881
Yang di atas ini sekarang, selama limapuluh tahun belakangan, telah menjadi semboyan gerakan klas-pekerja Inggris. Ia telah berjasa sekali pada waktu kebangkitan Serikat-Serikat Sekerja setelah penolakan Undang-Undang Kombinasi yang jahat pada tahun 1824; ia bahkan berjasa lebih besar lagi pada masa gerakan Chartis yang jaya, ketika kaum pekerja Inggris berbaris di depan klas pekerja Eropa. Tetapi zaman kini terus berlalu, dan sangat banyak hal yang dihasratkan dan diperlukan limapuluh tahun, dan bahkan tigapuluh tahun yang lalu, kini sudah ketinggalan jaman dan akan sepenuhnya tidak pada tempatnya. Adakah semboyan lama yang selama ini dikibarkan itu juga termasuk di situ?
Upah sehari yang layak bagi kerja sehari yang layak? Tetapi, apakah upah sehari yang layak itu, dan apakah kerja sehari yang layak itu? Bagaimana mereka itu ditentukan oleh hukum-hukum yang mendasari keberadaan masyarakat modern dan yang mengembangkannya? Sebagai jawaban atas pertanyaan ini jangan kita bersandar pada ilmu pengetahuan moral atau hukum dan keadilan, atau pada sesuatu perasaan kemanusiaan yang sentimental, kewajaran, atau bahkan kedermawanan yang secara moral layak, yang bahkan adil menurut hukum, mungkin sekali sangat jauh daripada layak secara sosial. Kelayakan atau ketidak-layakan sosial ditentukan oleh satu ilmu pengetahuan saja-ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kenyataan-kenyataan material dari produksi dan pertukaran, ilmu pengetahuan ekonomi politik.
Nah, apakah yang disebut ekonomi-politik sebagai upah sehari yang layak dan kerja sehari yang layak itu? Hanyalah tingkat upah-upah dan lamanya dan intensitas kerja sehari yang ditentukan oleh persaingan dan pemberi-kerja dan yang dipekerjakan di pasar terbuka. Dan apakah mereka itu, jika ditentukan sedemikian?
Upah sehari kerja, dalam kondisi-kondisi normal, ialah jumlah yang diperlukan oleh pekerja untuk memperoleh bekal-bekal kehidupan (means of existence) yang diperlukan, sesuai standar hidup; kedudukan dan negeri, dan untuk menjaga agar dirinya dalam kemampuan kerja dan untuk mengembang-biakkan kaumnya (race). Tingkat upah-upah yang nyata (aktual), dengan fluktuasi-fluktuasi perdagangan, kadang-kadang mungkin di atas, kadang-kadang di bawah tingkat ini; tetapi, dalam keadaan-keadaan layak, tingkat itu seharusnya merupakan rata-rata semua ayunan (oskilasi).
Kerja sehari yang layak ialah lamanya hari kerja dan intensitas kerja sesungguhnya yang dicurahkan tenaga kerja sehari penuh seorang pekerja tanpa melanggar batas kapasitasnya bagi jumlah kerja yang sama untuk hari berikutnya dan seterusnya.
Maka, transaksi itu dapatlah digambarkan sebagai berikut-si pekerja memberikan kepada Kapitalis tenaga kerja sehari penuhnya; yaitu, sebanyak darinya yang dapat diberikannya tanpa menyebabkan ketidak-mungkinan pengulangan terus-menerus transaksi itu. Sebagai penukarnya pekerja tersebut menerima imbalannya, tidak lebih dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang diperlukan untuk menjaga pengulangan transaksi yang sama setiap hari (berikutnya). Si pekerja memberikan sekian itu, Kapitalis memberikan sesedikit itu, sesuai yang diperkenankan dari transaksi tersebut. Ini merupakan jenis kelayakan yang sangat khas.
Tetapi, marilah kita lebih mencermati hal ini. Karena menurut para ekonom-politik, upah-upah dan hari-hari kerja ditetapkan oleh persaingan, maka kelayakan tampaknya menuntut bahwa kedua belah pihak mesti mempunyai awalan yang sama layaknya secara sama-derajat. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Si Kapitalis, jika ia tidak dapat sepakat dengan si Pekerja, dapat saja menunggu, dan hidup dari modalnya. Si Pekerja tidak berkemampuan begitu. Baginya hanya ada upah-upah itu untuk hidup, dan oleh karenanya mesti menerima pekerjaan kapan saja, di mana saja, dan dengan syarat-syarat apa saja yang dapat diperolehnya. Si Pekerja tidak menikmati/memiliki awalan yang layak. Ia sangat dirundung ketakutan akan kelaparan. Namun begitu, menurut ekonomi politik klas Kapitalis, demikian itulah warna sebenarnya dari kelayakan itu.
Tetapi ini baru sebagian kecil saja. Penerapan tenaga mekanik dan mesin dalam pekerjaan-pekerjaan baru, dan perluasan dan perbaikan-perbaikan mesin dalam usaha-usaha yang sudah menggunakannya, terus menggusur semakin banyak "tangan" (pekerja); dan itu terjadi dalam laju yang jauh lebih cepat daripada laju "tangan-tangan" itu dapat diserap oleh, dan menemukan pekerjaan di dalam, usaha-usaha manufaktur negeri bersangkutan. "Tangan-tangan" yang digantikan ini membentuk barisan cadangan industrial yang sesungguhnya untuk kegunaan Modal. Jika perdagangan sedang buruk, mereka itu bisa kelaparan, mengemis, mencuri, atau ke tempat-kerja; jika perdagangan sedang baik, mereka siap (dipakai) untuk meluaskan produksi; dan hingga laki-laki, perempuan atau anak terakhir dari barisan cadangan (tenaga kerja cadangan) ini akan memperoleh pekerjaan-yang, hanya terjadi pada masa-masa kekalutan over-produksi-hingga di situlah persaingannya akan menekan upah-upah, dan dengan keberadaannya saja memperkuat kekuasaan Modal dalam pergulatannya dengan Kerja. Dalam perlombaan dengan Modal itu, Kerja tidak saja berintangan, ia harus pula menyeret sebuah bola-besi raksasa yang dikelingkan pada kakinya. Namun ini (pun) adalah layak menurut ekonomi politik Kapitalis.
Tetapi, mari kita meneliti dari dana apakah Modal (Capital) membayar upah-upah yang sangat layak ini? Dari modal, tentu saja. Tetapi, modal tidak menghasilkan nilai. Kerja, di samping tanah, adalah sumber kekayaan satu-satunya; modal itu sendiri tidak lain dan tidak bukan hanyalah tumpukan/timbunan hasil kerja. Sehingga upah-upah Kerja dibayar dari kerja, Dan si pekerja dibayar dari hasil (kerja)-nya sendiri. Menurut yang dapat kita sebut kelayakan umum, upah-upah pekerja semestinya terdiri atas produk (hasil) kerjanya sendiri. Tetapi itu tidak akan layak menurut ekonomi politik. Sebaliknya, hasil kerja pekerja pergi kepada Kapitalis, Dan si pekerja mendapatkan dari situ tidak lebih daripada kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan. Dan demikianlah kesudahan perlombaan persaingan yang luar-biasa layak ini adalah bahwa hasil kerja dari yang melakukan pekerjaan secara tidak-terelakkan lagi berakumulasi di tangan-tangan mereka yang tidak bekerja, dan di tangan mereka itu menjadi alat yang paling kuasa untuk memperbudak justru orang-orang yang menghasilkannya.
Upah sehari yang layak bagi kerja sehari yang layak! Masih banyak lagi yang dapat disampaikan mengenai kerja sehari yang layak itu, yang kelayakannya sepenuhnya setara dengan kelayakan upah-upah itu. Tetapi hal ini mesti kita bicarakan di lain kesempatan. Dari yang diuraikan di atas, jelas sekali bahwa semboyan lama itu telah kedaluwarsa, dan dewasa ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kelayakan ekonomi politik, yaitu sebagaimana yang dengan sebenar-benarnya menentukan hukum-hukum yang menguasai masyarakat sekarang, kelayakan itu sepenuhnya ada pada satu pihak-pada pihak Modal.
Maka itu, biarlah semboyan lama itu dikubur untuk selama-selamanya dan digantikan dengan semboyan lain:
PEMILIKAN ATAS ALAT-ALAT KERJA-BAHAN MENTAH, PABRIK-PABRIK, MESIN-MESIN-OLEH RAKYAT PEKERJA SENDIRI.
ooo0ooo
Kaum Proletar Industri
Friedrich Engels
(The Conditions Of The Working-Class In England)
Urutan penyelidikan kita terhadap berbagai golongan proletar yang berbeda dengan sendirinya mengikuti sejarah kebangkitannya dalam bab terdahulu. Golongan proletar yang pertama sekali muncul dihubungkan dengan industri manufaktur, dilahirkan dari sini, dan dengan sendirinya, mereka yang bekerja di dalam sektor ini, dalam pekerjaan mengolah bahan mentah, akan pertama sekali menarik minat kita. Produksi bahan mentah dan bahan bakar bagi industri manufaktur menjadi penting hanya sebagai akibat dari perubahan industri, serta melahirkan golongan proletar baru: penambang batubara dan metal. Kemudian, yang ketiga, industri manufaktur mempengaruhi pertanian, dan keempat, kondisi Irlandia; sehingga masing-masing fraksi proletar akan memperoleh tempat dengan sendirinya. Kita juga akan menemukan bahwa, mungkin kecuali pada orang-orang Irlandia, tingkat kecerdasan berbagai buruh memiliki proporsi yang berkaitan langsung dengan hubungan mereka dengan industri manufaktur; dan bahwa buruh pabrik merupakan kelompok yang paling cerdas sesuai dengan kepentingan mereka, buruh tambang sedikit di bawahnya, sedangkan buruh pertanian hampir tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Kita akan kembali menemukan urutan yang sama pada buruh industri, serta melihat bagaimana buruh pabrik, yang merupakan anak-anak sulung revolusi industri, sejak semula hingga saat ini telah membentuk inti Gerakan Buruh, dan bagaimana buruh-buruh lainnya kemudian bergabung dengan gerakan ini hanya sebagaimana barang hasil kerajinan tangan mereka telah disingkirkan oleh kemajuan penemuan mesin. Begitulah, kita akan mengambil pelajaran dari contoh-contoh yang ditawarkan Inggris, dari langkah sejajar yang telah dipertahankan oleh Gerakan Buruh dengan gerakan perkembangan industri, yang merupakan arti penting sejarah industri manufaktur.
Meskipun demikian, karena dewasa ini kaum proletar industri sangat terlibat dalam gerakan buruh, dan karena kondisi berbagai golongan ini umumnya hampir sama, karena mereka semua adalah kaum proletar industri, mula-mula kita harus mempelajari kondisi kaum proletar industri secara keseluruhan, agar dapat kemudian memperhatikan secara lebih khusus masing-masing golongan secara terpisah dengan kekhasannya sendiri-sendiri.
Sebelumnya telah dikemukakan bahwa industri manufaktur memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang. Industri ini membutuhkan modal besar untuk mendirikan perusahaan kolosal yang menghancurkan borjuasi pedagang kecil dan untuk menaklukkan kekuatan-kekuatan Alam, dengan demikian menyingkirkan pekerjaan manual pekerja-pekerja independen dari pasaran kerja. Pembagian kerja, penggunaan air dan terutama uap, serta pengunaan mesin-mesin, adalah tiga tuas (pengungkit) utama yang digunakan oleh industri manufaktur, sejak pertengahan abad yang lalu, untuk mengobrak-abrik dunia. Dalam skala kecil, industri manufaktur melahirkan kelas menengah; dalam skala besar, ia melahirkan kelas buruh, dan mengangkat orang-orang terpilih dari kelas menengah ke atas tahta, namun hanya untuk ditumbangkan kembali bila saatnya tiba. Sementara itu, tidak dapat dipungkiri dan mudah untuk dijelaskan bahwa sejumlah besar golongan kelas menengah kecil yang berasal dari "masa lalu yang menyenangkan" telah dilenyapkan oleh industri manufaktur, dan dilebur menjadi kapitalis kaya di satu pihak dan buruh miskin di lain pihak.*)
Meskipun demikian, kecenderungan pemusatan oleh industri manufaktur tidak hanya berhenti di sini saja. Penduduk menjadi tersentralisir, sama halnya seperti modal; dan, secara sangat alamiah, tentunya, sebab manusia, para buruh, dalam industri manufaktur dipandang hanya sebagai sepotong modal yang untuk pemakaiannya pemilik pabrik membayar sejumlah bunga dengan nama 'upah.' Sebuah pabrik manufaktur membutuhkan buruh dalam jumlah besar untuk dipekerjakan bersama-sama dalam satu bangunan, tinggal berdekatan satu sama lain dan pada pabrik-pabrik berukuran besar membentuk perkampungan sendiri. Mereka memiliki kebutuhan-kebuthan, yang untuk pemenuhannya diperlukan orang lain lagi; maka berdatanganlah para pengrajin-tangan, pengrajin sepatu, penjahit, tukang roti, tukang kayu, tukang batu. Penghuni kampung-kampung ini, terutama generasi mudanya, membiasakan diri pada kerja pabrik, menjadi trampil di dalamnya, dan ketika pabrik pertama tidak lagi dapat menampung mereka semua, tinghkat upah menjadi turun, dan akibatnya adalah terjadi perpindahan pabrik-pabrik manufaktur baru. Maka perkampungan itu tumbuh menjadi sebuah kota kecil, dan kota kecil ini kemudian tumbuh menjadi kota besar. Makin besar kota tersebut, makin banyak pula keuntungannya. Kota ini akan membangun jalan-jalan raya, jalan kereta api, kanal. Pilihan akan buruh trampil secara konstan meningkat, pabrik-pabrik baru dapat dibangun dengan biaya lebih murah karena adanya persaingan di antara para kontraktor bangunan dan mesin yang ada, daripada jika dibangun di distrik yang letaknya jauh di pinggiran kota sebab artinya kayu-kayu, mesin-mesin, kontraktor bangunan dan petugas-petugas harus diangkut ke sana. Kota ini akan menawarkan sebuah pasar yang akan dibanjiri pembeli, serta komunikasi langsung dengan pasar-pasar yang memasok bahan mentah atau memerlukan barang jadi. Demikianlah pertumbuhan cepat dan luar biasa dari kota-kota industri manufaktur. Daerah pedesaan atau pinggiran kota, di lain pihak, memiliki keuntungan tingkat upah yang lebih rendah daripada di kota, sehingga kota dan desa selalu berada dalam persaingan. Dan, apabila keuntungan berada di pihak kota hari ini, tingkat upah akan menjadi sangat rendah di desa besok, sehingga investasi akan lebih menguntungkan untuk dibangun di desa. Akan tetapi kecenderungan pemusatan dari industri manufaktur terus berlangsung dengan kekuatan penuh, dan setiap pabrik baru yang dibangun di desa membawa serta sebuah kuman kota manufaktur. Seandainya memungkinkan bagi desakan industri manufaktur gila-gilaan ini untuk tetap berlangsung dalam kecepatannya saat ini sampai satu abad mendatang, maka setiap distrik industri manufaktur di Inggris akan menjadi sebuah kota besar industri manufaktur, dan daerah Manchester dan Liverpool akan bertemu di Warrington atau Newton; sebab dalam perdagangan pun pemusatan penduduk seperti ini terjadi dengan cara yang persis sama, dan itulah sebabnya satu atau dua pelabuhan besar seperti Hull dan Liverpool, Bristol dan London, memonopoli hampir seluruh perdagangan maritim di Inggris Raya.
Karena perdagangan dan industri manufaktur mencapai perkembangannya yang paling lengkap di kota-kota besar ini, pengaruhnya terhadap kaum proletar pun paling mudah dilihat di sini. Di sini, pemusatan kekayaan mencapai tingkat paling tinggi; di sini moral dan kebiasaan 'masa lalu yang menyenangkan' paling banyak terhapus; segalanya telah berkembang sedemikian rupa di sini sehingga sebutan Merry Old England (Inggris Tua yang Ceria) sudah tidak ada artinya lagi, sebab nama 'Inggris Tua' sendiri sudah tidak lagi dikenal dan tidak lagi terdapat dalam cerita-cerita tentang kakek-kakek kita. Dengan demikian pula, yang ada tinggal kelas kaya dan kelas miskin, sebab kelas menengah-bawah semakin lenyap samasekali dengan berlalunya hari. Maka kelas yang tadinya paling stabil telah menjadi kelas yang paling gelisah. Dewasa ini, kelas ini terdiri dari beberapa orang sisa-sisa masa lampau, dan sejumlah orang yang bersemangat mencari harta kekayaan, para Micawbers dan spekulan industri yang satu diantaranya mungkin berhasil mengumpulkan kekayaan, sementara sembilanpuluh-sembilan lainnya jatuh pailit, dan lebih dari separuh dari sembilan-puluh-sembilan ini selamanya hidup dengan cara mengulangi kegagalan.
Namun di kota-kota ini, kaum proletar merupakan mayoritas tak terhingga, dan bagaimana mereka menjalani hidupnya, pengaruh apa saja yang diberikan kota-kota ini terhadap mereka, akan kita selidiki sekarang.
Catatan:
*) Sampai di sini, bandingkan dengan artikel saya "Garis Besar bagi Kritik Ekonomi Politik" dalam Deutsch-Franzosische Jahrbucher. (Lihat juga Marx/Engels, Gesamtausgabe, Abt. I, Bd. II, S. 379-404.-Ed.) [Dalam essay ini "persaingan bebas" merupakan titik awal pembahasan; akan tetapi industri hanyalah merupakan praktek persaingan bebas dan persaingan bebas hanyalah merupakan prinsip industri itu sendiri. (Ditambahkan di dalam edisi berbahasa Jerman.)]
Keruntuhan Feodalisme dan Kebangkitan Negara-Negara nasional
Moskow, 1956
Bagian dari Bab IV Perang Tani di Jerman edisi Inggris, FLPH,
Ketika pertempuran-pertempuran buas yang dilakukan oleh kaum bangsawan feodal yang berkuasa mengisi suasana Zaman Tengah dengan keriuhannya, dalam saat bersamaan pekerjaan tak bersuara dari klas-klas tertindas menggerogoti sistem feodal di seluruh Eropa Barat dan menciptakan syarat-syarat di mana makin sempit ruang yang tersisa untuk tuan feodal. Benar, kalangan tuan-tuan itu masih terus seperti sediakala di pedesaan, yaitu menyiksa hamba-hamba mereka, hidup mewah berkat keringat para hamba itu, menunggang kuda menerjang roboh tanaman-tanaman mereka yang hampir panen dan memperkosa istri serta anak-anak perempuan mereka. Tetapi kota besar dan kecil bermunculan di mana-mana: di Italia, di Perancis Selatan, dan di sepanjang sungai Rhein kota-kota tersebut adalah kota-kota utama Romawi yang dibangunkan dari keruntuhannya; di tempat lain, terutama di Jerman pedalaman, kota-kota itu dibangun kembali. Terlindung oleh tembok dan parit, kota-kota itu merupakan basis yang lebih hebat ketimbang benteng-benteng kaum bangsawan, karena basis-basis itu hanya dapat direbut dengan menggunakan kelompok yang besar. Di belakang tembok dan parit, tergabung dalam gilda-gilda dan dalam ukuran yang cukup kecil, berkembang kerajinan tangan Jaman Tengah. Terjadi akumulasi kapital yang pertama, dan lambat laun timbul kebutuhan akan perdagangan dengan kota-kota lain dan dengan daerah-daerah lain di dunia ini, dan dengan itu alat-alat untuk melindungi perdagangan tersebut.
Pada abad ke limabelas orang-orang kota mutlak sudah lebih diperlukan bagi masyarakat ketimbang kaum bangsawan feodal. Benar, pertanian tetap merupakan pekerjaan sebagian besar rakyat, dan dengan begitu, cabang utama dari produksi. Tetapi petani-petani merdeka yang di sana-sini berhasil dapat mempertahankan diri terhadap pelanggaran dari kaum bangsawan, adalah bukti yang meyakinkan bahwa dalam pertanian hal yang terpenting bukan terletak pada kelambanan dan pemerasan ala lintah-darat dari kaum bangsawan, tetapi pada kerja membanting-tulang dari kaum tani. Dan lagi, keperluan-keperluan kaum bangsawan itu sendiri telah berlipat-ganda juga dan berubah, sehingga kota-kota mutlak telah menjadi diperlukan bagi mereka pula; bukankah perkakas-perkakas produksinya yang satu-satunya, lapisbesi pelindung dan senjatanya, diperoleh di kota-kota? Kain tenunan dalam negeri, perabotan dan perhiasan, sutera Italia, renda Brabant, bulu binatang daerah utara, minyak wangi Arabia, buah-buahan Levantin dan rempah-rempah India-semuanya, kecuali sabun-dibeli oleh kaum bangsawan di kota. Suatu perdagangan dunia tertentu telah berkembang; orang-orang Italia berlayar ke Laut Tengah dan pantai Atlantik hingga Flander, dan kota-kota Hanseatik menguasai Laut Utara dan Laut Baltik dengan menghadapi persaingan yang makin hebat dari Belanda dan Inggris. Hubungan darat dipelihara terus antara pusat-pusat utara dan selatan dari lalulintas laut; jalan-jalan raya bagi mereka melintasi Jerman. Sedang kaum bangsawan makin menjadi lebih tak ada gunanya lagi dan makin lebih menjadi halangan bagi perkembangan, maka dalam pada itu warga kota menjadi suatu klas yang menjelmakan perkembangan selanjutnya dari produksi dan perdagangan, pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial dan politik.
Segala kemajuan ini yang diakibatkan oleh produksi dan pertukaran adalah, memang, dibandingkan dengan ukuran saat ini, bersifat sangat terbatas. Produksi hanya terbatas pada gilda-gilda, dengan demikian masih mengandalkan watak feodalnya, dan perdagangan terbatas pada laut-laut Eropa; yang tidak meluas melampaui pelabuhan-pelabuhan laut Levantin, di mana hasil-hasil dari Timur Jauh dipertukarkan. Tetapi gilda-gilda, meskipun kecil dan terbatas, dan bersama itu anggota-anggota gilda, cukup kuat untuk membentuk kembali masyarakat feodal, dan paling tidak terus bergerak, sedang kaum bangsawan macet.
Lagi pula, kaum warga kota mempunyai uang-senjata perkasa terhadap feodalisme. Hampir-hampir tidak ada suatu tempat untuk uang di dalam usaha pertanian feodal di masa awal Jaman Tengah. Si tuan memperoleh segala yang dibutuhkan untuknya dari para hambanya, baik dalam bentuk kerja, maupun sebagai hasil jadi; para perempuan menenun rami dan bulu domba, dan memproduksi bahan pakaian; kaum laki-laki mengerjakan tanah ladang, anak-anak menggembala ternak sang tuan, dan mengumpulkan buah-buah dari hutan, sarang burung dan jerami; di samping itu, seluruh keluarga masih harus menyetorkan gandum, buah-buahan, telur, mentega, keju, unggas, hewan piaraan, dan barang-barang lain yang tak terhitung. Setiap rumah feodal sanggup mencukupi diri; sampai pula pembiayaan militer pun dimintakan dalam bentuk hasil bumi; perdagangan dan pertukaran belum ada, dan uang adalah sesuatu yang berlebihan. Eropa telah jatuh ke derajat yang begitu rendah, ia telah memulai segalanya begitu antusias dari awal lagi, sehingga saat itu uang lebih banyak semata-mata berfungsi politik ketimbang berfungsi sosial: uang digunakan untuk membayar pajak, dan pada dasarnya diperoleh melalui perampokan di jalan raya.
Namun semua itu berubah. Uang menjadi perantara umum untuk pertukaran lagi, dan bagiannya yang terbesar, karena itu, berlipat ganda secara besar-besaran; bahkan kalangan tuan-tuan pun tak dapat hidup lagi tanpa uang, dan karena mereka hanya mempunyai sedikit atau sama sekali tidak punya apapun untuk dijual, dan karena perampokan-perampokan di jalan raya tidak begitu mudah dilakukan lagi, mereka terpaksa lari pada lintah darat kota. Lama sebelum alat-alat perang baru menembak menggempur tembok-tembok puri ksatria-feodal, tembok-tembok ini sudah digerogoti oleh uang; memang, serbuk peledak, boleh dikatakan, hanyalah pelaksanaan dalam pengabdian terhadap uang. Uang adalah alat politik yang besar di tangan kaum warga kota. Di mana hubungan-hubungan antara orang dengan orang didesak dan dikuasai oleh hubungan-hubungan uang, di mana cukai hasil bumi diganti oleh pembayaran uang, di situlah hubungan-hubungan borjuis menggeser hubungan-hubungan feodal. Benar, ekonomi alamiah lama yang kejam itu pada umumnya masih berkuasa di pedesaan; tetapi telah muncul pula daerah-daerah utuh di mana kaum tani, seperti di negeri Belanda, Belgia dan Rhein hilir, membayar uang kepada tuan-tuan mereka dan bukan lagi rodi dan pungutan-paksa, di mana tuan dan vasal sudah mengadakan langkah pertama dan menentukan ke arah perubahan menjadi pemilik tanah dan penyewa, dan di mana, sebagai akibat darinya, lembaga-lembaga politik feodalisme mulai kehilangan dasar kemasyarakatannya juga di pedesaan.
Sampai derajat mana dalam abad ke limabelas feodalisme telah tergerogoti dan dari dalam diceraiberaikan oleh uang, dengan menyolok dicerminkan dalam kehausan akan emas yang pada masa itu menguasai Eropa Barat. Orang Portugal mencari emas di sepanjang pantai Afrika, di India, dan di seluruh Timur Jauh; emas adalah kata mujijat yang mendorong orang Spanyol menyeberangi Samudra Atlantik ke Amerika; emas adalah barang yang pertama-tama ditanyakan oleh orang kulit putih ketika mereka menginjakkan kakinya di tanah yang baru ditemukan. Dan hasrat akan perjalanan jauh dan petualangan untuk merebut emas ini, biarpun sudah begitu banyak terwujud pada mulanya dalam bentuk-bentuk feodal dan setengah-feodal, pada dasarnya sudah bertentangan dengan feodalisme, yang landasannya bertumpu pada pertanian, dan yang perebutan-perebutannya pada hakekatnya tertuju pada memperoleh tanah. Dan lagi, berlayar di laut adalah nyata-nyata pekerjaan borjuis, yang meninggalkan jejak bekasnya yang anti-feodal juga pada setiap angkatan laut modern.
Demikianlah maka pada abad ke limabelas feodalisme berada dalam keruntuhan yang sempurna di seluruh Eropa Barat. Kota-kota dengan kepentingan-kepentingan anti-feodal, dengan undang-undangnya sendiri dan kaum wargakotanya yang bersenjata, telah menancapkan dirinya dan menembus ke dalam wilayah-wilayah feodal di manapun, dan telah menjadikan sebagian tuan-tuan feodal tergantung pada mereka secara sosial, melalui uang, dan di sana-sini bahkan juga secara politik. Sampai pula di lingkungan-lingkungan di mana teristimewa syarat-syarat menguntungkan telah memberikan sumbangannya kepada kemajuan pertanian, ikatan-ikatan feodal lama telah mulai kendor di bawah pengaruh uang; hanya di negeri-negeri yang baru direbut, seperti jajahan-jajahan Jerman di sebelah timur sungai Elbe, atau kalau tidak di daerah-daerah terbelakang yang jauh dari lalu-lintas perdagangan, kaum bangsawan berjalan terus sebagaimana di waktu lampau. Di mana pun-di kota dan desa-terdapat makin banyak orang di atas segala peperangan yang silih berganti dan bodoh itu, dihentikannya permusuhan-permusuhan feodal yang mengekalkan adanya perang dalam negeri bahkan di waktu musuh asing ada di dalam negeri, dan dihentikannya keadaan yang berupa pembinasaan tak henti-henti dan tak berperasaan yang berlangsung selama Jaman Tengah. Masih terlalu lemah untuk menyatakan serta mempertahankan kehendaknya, anasir-anasir ini menemukan dukungan kuat pada anak-tangga teratas dari seluruh sistem feodal-kekuasaan raja itu sendiri. Dan dengan begitu maka meningkatkan studi tentang syarat-syarat kemasyarakatan kepada syarat-syarat negara, dan pergilah kita meninggalkan bidang ekonomi ke bidang politik.
Lambat laun berkembang nasionalitas-nasionalitas baru dari kekacau-balauan suku-suku bangsa di masa paling awal dari Jaman Tengah, suatu proses di mana pemenangnya dikatakan telah dicernakan oleh yang dikalahkan di sebagian terbesar daerah yang dahulunya adalah propinsi-propinsi Romawi, yaitu, tuan Jerman oleh kaum tani dan orang-orang kota. Nasionalitas-nasionalitas modern dengan begitu adalah juga hasil dari klas-klas tertindas. Bagaimana perpaduan terjadi di sini dan pembagian di sana, ditunjukkan secara grafik dalam peta Lorraine Tengah2) buatan Menke. Seorang hanya perlu mengikuti garis pembagi antara nama-nama Romawi dan Jerman untuk mendapatkan bahwa garis itu sejalan dengan, pada pokoknya, batas antara bahasa Perancis dan Jerman, yang ada selama seratus tahun di Belgia dan Lorraine Bawah.
Ada daerah sempit yang dipertengkarkan di sana-sini di mana dua bahasa itu bertempur merebut keunggulan; tetapi pada keseluruhannya adalah ditegaskan dengan baik apa yang Jerman dan apa yang Romawi. Tetapi bentuk Jerman tinggi dan Perancis rendah lama dari bagian terbesar nama-nama di peta tersebut menunjukkan bahwa nama-nama itu tergolong pada abad ke sembilan, atau selambat-lambatnya, pada abad ke sepuluh, dan bahwa batas antara mereka itu pada hakekatnya sudah diletakkan menjelang akhir periode Karolinga. Pada pihak Romawi, teristimewa di dekat batas bahasa, terdapat nama-nama campuran yang terjadi dari nama Jerman dan nama ilmu bumi Romawi; misalnya, di sebelah barat Maas dekat Verdun, Rofridi curtis, Ingolini curtis, Teudegisilo villa, sekarang bernama Ippecourt, Recourt la Creux, Amblainecourt sur Aire, Thierville. Itu semua adalah adalah wilayah-wilayah Frangkonia, koloni-koloni kecil Jerman di wilayah Romawi, yang cepat atau lambat menjadi di-Romawi-kan. Di kota-kota, dan di beberapa lingkungan pedesaan, terdapat koloni-koloni Jerman yang lebih kuat, yang mempertahankan bahasanya selama jangka waktu yang lebih lama; salah satu koloni semacam itu, misalnya, menghasilkan "Ludwigslied"3) dalam bagian akhir abad ke sembilan; tetapi sumpah-sumpah raja-raja dan orang-orang besar dalam tahun 842 Masehi, yang di dalamnya bahasa Romawi sudah menjadi bahasa resmi Frangkonia, membuktikan bahwa sejumlah sangat besar tuan-tuan Frangkonia telah di-Romawi-kan lebih dahulu.
Sekali kelompok-kelompok bahasa itu dibatasi (kesampingkan perang-perang perebutan dan pembinasaan yang terjadi kemudian, seperti yang dipertarungkan dengan orang-orang Slav Elbe),4) maka wajarlah bahwa kelompok-kelompok bahasa itu akan berperanan sebagai dasar untuk pembentukan negara, dan bahwa nasionalitas-nasionalitas mulai berkembang menjadi bangsa (nasion). Keruntuhan yang cepat dari negara campuran Lorraine menunjukkan bagaimana kuatnya proses spontan ini sudah dalam abad ke sembilan. Benar, sepanjang seluruh Jaman Tengah batas-batas bahasa sama sekali tidak berpadu dengan batas-batas negara, namun setiap nasionalitas, terkecuali Italia barangkali, diwakili dalam suatu negara besar Eropa yang spesifik, dan kecenderungan untuk mendirikan negara nasional, yang tampil lebih jelas lagi dan lebih sadar, merupakan satu di antara pengungkit-pengungkit yang paling hakiki dari kemajuan di masa Jaman Tengah.
Di dalam setiap negara macam Jaman Tengah ini raja mewakili anak-tangga teratas dari seluruh hirarki feodal, seorang kepala tertinggi yang mutlak diperlukan bagi vasal-vasal, tetapi yang terhadapnya mereka itu selalu dalam keadaan berontak terus-menerus. Hubungan-hubungan terutama dalam ekonomi feodal, yaitu hak mengusahakan tanah dengan upeti-upeti serta kerja-wajib perseorangan tertentu, tidak kurang memberikan dasar-dasar bagi pertentangan-pertentangan dalam bentuk yang paling sederhana, teristimewa di mana begitu banyak orang berkepentingan dalam hal mendapatkan alasan untuk bersitegang. Niscaya, karena Jaman Tengah, di mana hubungan-hubungan hak di semua negeri merupakan suatu kekusutan yang membingungkan berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diakui, dicabut, diperbarui, dibatalkan, diubah dan dengan cara lain diterapkan? Karel Pemberani, misalnya, adalah pemakai tanah Kaisar untuk sebagian dari tanahnya, dan pemakai tanah raja Perancis untuk sebagian lainnya lagi; pada lain pihak, raja Perancis, orang yang memberi hak-pakai tanah kepadanya, bersamaan dengan itu adalah pemakai tanah Karel Pemberani, vasal-nya sendiri, untuk daerah-daerah tertentu. Bagaimanakah bentrokan-bentrokan dapat dielakkan? Maka itu pergantian berabad-abad terikatnya kaum vasal kepada pusat kerajaan, yang itu sendiri sudah dapat melindungi mereka terhadap musuh-musuh dari luar dan terhadap satu sama lain, dan pergantian berabad-abad penolakan mereka terhadap pusat itu, sehingga hal terikat tadi dengan tak terelakkan dan selalu senantiasa berubah menjadi penolakan; maka itu perjuangan yang terus-menerus antara raja dengan vasal, yang riuh menjemukan itu menghanyutkan segala sesuatu lainnya selama waktu yang panjang ketika perampokan merupakan sumber satu-satunya dari pendapatan yang dianggap layak bagi orang-orang merdeka; maka itu terjadi penghianatan, pembunuhan, racun, komplotan dan kebencian berlarut apa pun yang mungkin, yang mendasari pikiran puitis dari ke-ksatriaan feodal dan biarpun begitu bukan rintangan untuk berbicara tentang kehormatan dan kesetiaan.
Terang sudah bahwa dalam kekacauan umum ini kekuasaan raja adalah unsur yang progresif. Ia mewakili susunan tata-tertib dalam keadaan kacau, dan nasion yang sedang bertumbuh dihadapkan pada keterpisahan menjadi negara-negara vasal yang memberontak. Semua anasir revolusioner yang terbentuk di bawah permukaan feodal cenderung mendukung raja sama banyaknya seperti yang menolaknya. Persekutuan raja dengan warga kota sudah mulai sejak abad ke sepuluh; sering diganggu oleh berbagai bentrokan, karena dalam Jaman Tengah tidak satupun menempuh jalan secara konsekuen, persekutuan setiap kali diperbarui lebih kokoh dan lebih teguh, sampai ia menolong raja mencapai kemenangannya yang terakhir, dan raja, sebagai pernyataan terima kasih, menaklukkan dan merampok sekutunya.
Raja, seperti juga kaum warga kota, mendapatkan dukungan sangat kuat dari para ahli hukum. Dengan penemuan-kembali hukum Romawi maka berkembang suatu pembagian kerja antara alim-ulama, penasehat legal di masa feodal, dan para ahli hukum keduniawian. Para ahli hukum baru ini di atas segalanya pada hakekatnya adalah suatu lembaga borjuis; dan, lagi pula, peradilan yang mereka pelajari, maju dan terpakai, pada hakekatnya adalah anti-feodal dan, dalam hal tertentu, berjuis. Hukum Romawi sejauh itu adalah pernyataan yuridis klasik mengenai syarat-syarat hidup dan benturan-benturan di dalam masyarakat yang istimewa dikuasai oleh milik perseorangan, sehingga segala perundang-undangan kemudian tidak mampu berkembang dengan berlandaskan padanya dengan jalan wajar dan layak. Tetapi hal milik warga kota selama Jaman Tengah masih kuat dikepung oleh pembatasan-pembatasan feodal, dan, misalnya, sebagian terbesar berupa hak-hak istimewa. Karena itu Hukum Romawi, dalam hal ini adalah jauh lebih maju daripada hubungan-hubungan borjuis di masa itu. Tetapi semua perkembangan sejarah selanjutnya dari hak milik borjuis hanya dapat, seperti halnya yang terjadi, bergerak maju ke arah hak milik perseorangan sejati. Perkembangan ini tentu mendapatkan suatu pengungkit yang kuat dalam hukum Romawi, yang memuat dalam bentuk sudah jadi segala sesuatu yang dengan tidak sadar masih dicari-cari oleh kalangan wargakota dalam paruh akhir dari Jaman Tengah.
Benar, dalam banyak hal hukum Romawi memberikan dalih untuk penindasan yang lebih berat terhadap kaum tani oleh kaum bangsawan. Ini adalah demikian, misalnya, bilamana saja kaum tani tidak dapat menunjukkan bukti tertulis tentang kebebasannya dari upeti-upeti secara lain yang sudah lazim, namun hal ini tidak mengubah keadaan. Kaum bangsawan pasti mendapatkan berbagai dalih semacam itu, dan memang setiap saat selalu mendapatkannya, tanpa hukum Romawi. Setidak-tidaknya, adalah suatu kemajuan yang sangat pesat bahwa diberlakukan suatu hukum yang tidak memikirkan hubungan-hubungan feodal dan sepenuhnya mengharapkan hak milik perseorangan yang modern.
Kita telah melihat bagaimana kaum bangsawan feodal di bidang ekonomi telah berlebihan, dan malah merupakan rintangan, dalam masyarakat semasa paruh akhir Jaman Tengah, dan bagaimana, di bidang politik pun juga, ia menjadi penghalang bagi perkembangan kota, dan perkembangan negara-negara nasional, yang pada masa itu hanya mungkin dalam bentuk monarkhi. Tetapi biarpun demikian ia masih dapat ditegakkan oleh monopolinya atau keahlian-perang; tak ada perang yang dapat dilakukan, tak ada pertempuran yang dapat diadakan, tanpa itu. Inipun harus berubah: langkah terakhir yang harus dibuat untuk menunjukkan kepada para bangsawan feodal bahwa periode dominasi mereka di bidang sosial dan politik sudah berakhir, bahwa mereka tidak dibutuhkan lagi dalam kedudukannya sebagai ksatria feodal, tidak juga di medan pertempuran.
Untuk memerangi sistem feodal dengan tentara feodal, yang di dalamnya serdadu-serdadunya terikat lebih erat kepada atasannya yang langsung daripada pada pimpinan tentara kerajaan, sudah terang akan berputar dalam lingkaran tak berujung-pangkal dan tak berakhir. Sudah sejak permulaan abad ke empatbelas raja-raja berupaya untuk menghapuskan pengelompokan-pengelompokan feodal semacam itu, dan mendirikan tentara-tentara mereka sendiri. Bagian di dalam tentara kerajaan yang terdiri dari pasukan-pasukan terdaftar dan sejak itu serdadu-serdadu sewaan senantiasa semakin besar. Pertama-tama mayoritas mereka itu adalah serdadu-serdadu jalan-kaki, orang-orang gelandangan dari kota dan hamba-hamba yang lari, orang-orang Lombardia, Genoa, Jerman, Belgia, dsb., digunakan dalam merebut kota dan untuk tugas-tugas dalam kota, dan mula-mula jarang sekali berguna dalam pertempuran terbuka. Tetapi pada akhir Jaman Tengah kita mendapati juga orang-orang berkuda yang bekerja mencari bayaran pada pengeran-pangeran asing dengan para pengikut mereka yang terhimpun dengan cara entah bagaimana, dan dengan itu memberi pertanda tentang kemusnahan yang tak terelakkan dari keahlian-perang feodal.
Bersamaan waktu dengan itu syarat pokok untuk pasukan jalan kaki yang cukup mampu untuk berperang, tercipta di kota-kota, dan di kalangan kaum tani merdeka telah muncul hal seperti itu. Sampai saat itu para ksatria feodal dengan pengiring-pengiring berkuda bukan saja merupakan intinya, tetapi tentaranya itu sendiri; kerumunan-kerumunan orang yang menyertainya berupa serdadu-serdadu jalan kaki tidak masuk hitungan, dan timbul tersedia di medan terbuka hanya untuk maksud berkelahi atau merampok belaka. Selama feodalisme menempati puncak kejayaannya sampai pada akhir abad ke-13, pasukan berkudalah yang bertempur dan menentukan semua pertempuran. Tetapi sejak itu keadaan berubah, dan memang benar, serentak di berbagai tempat. Menghilangnya perhambaan secara berangsur-angsur di Inggris menimbulkan berbagai klas kaum tani merdeka, pemilik tanah dan penyewa, yang memberi bahan mentah untuk pasukan jalan kaki yang baru yang terampil menggunakan busur dan panah, senjata nasional Inggris pada masa itu. Mulai digunakannya secara umum para pemanah, yang selalu berperang dengan berjalan kaki, tak peduli menunggang kuda atau tidak selama dalam perjalanannya, menyebabkan munculnya suatu perubahan penting dalam taktik tentara Inggris. Dari abad ke-14 kaum ksatria feodal lebih suka bertempur dengan berjalan kaki di mana saja lapangan dan syarat-syarat lainnya mengarah ke situ. Di belakang barisan pemanah, yang membuka pertempuran dan mengusahakan kekacauan dalam barisan musuh, suatu barisan tentara yang padu terdiri dari ksatria-ksatria feodal yang tidak berkuda menunggu serangan musuh atau saat yang tepat untuk menyerang, sedangkan hanya sebagian dari mereka tetap menunggang kuda untuk melancarkan dukungan dengan serangan-serangan samping. Rangkaian kemenangan-kemenangan Inggris di Perancis pada masa itu secara prinsipil terletak pada hidupnya kembali anasir defensif di dalam tentara seperti tersebut di atas; dan kebanyakan adalah justru pertempuran-pertempuran yang sama bersifat defensif dengan pengaruh ofensif seperti halnya pertempuran-pertempuran Wellington di Spanyol dan Belgia. Sesudah Perancis menggunakan taktik baru-mungkin, sesudah penembak-penembak busur silang sewaan Italia dalam kelompok mereka mengisi tempat penembak-penembak busur Inggris-maka habislah kemenangan-kemenangan Inggris.
Sama dengan itu, pada awal abad ke-14 pasukan jalan kaki kota-kota Flandria memberanikan dirinya-dan seringkali dengan sukses-melawan kaum ksatria feodal Perancis dalam pertempuran terbuka, dan percobaan Kaisar Albrecht untuk membujuk kaum tani merdeka (reichsfreie) Swiss supaya berpihak kepada Archduke Austria, yaitu, dia sendiri, memberikan dorongan untuk pembentukan pasukan jalan kaki modern pertama yang tersohor di Eropa. Dalam segala kemenangan Swiss atas Austria, dan, patut dicatat, atas Burgundia, ksatria-ksatria feodal berbaju lapis besi-menunggang kuda atau secara lain-menderita pukulan-kembali terakhir di tangan serdadu-jalankaki, kelompokan feodal di tangan tentara modern yang sedang bertumbuh, ksatria feodal di tangan orang kota dan tani merdeka. Dan orang Swiss, sebagai penegasan tentang watak borjuis dari republik merdeka pertamanya di Eropa, segera mengubah kemashuran perangnya menjadi perak. Segala pertimbangan politiknya menguap; kanton-kanton berubah menjadi pusat pendaftaran serdadu-serdadu sewaan yang mencari penawaran tertinggi. Di lain tempat juga, dan khususnya di Jerman, genderang berbunyi gemuruh penuh nafsu memanggil serdadu-serdadu baru, tetapi sinisme suatu pemerintah, yang maksud satu-satunya ternyata adalah penjualan orang-orang penduduk negerinya, tetap tak ada bandingannya sampai saat para pangeran Jerman melampauinya ketika terjadi kemunduran nasional yang terdalam.
Kemudian, dalam abad ke-14 juga, bahan peledak dan senjata meriam diperkenalkan ke Eropa melalui Spanyol oleh orang Arab. Sampai akhir Jaman Tengah senjata api tetap tidak penting, dan begini memahaminya, karena busur para penembak-busur Inggris di Crecy menembak sama jauhnya juga dan barangkali lebih pasti-biarpun, barangkali, dengan hasil yang-biarpun, barangkali, dengan hasil yang kurang-daripada senapan berlaras-halus serdadu-serdadu jalankaki di Waterloo. Alat-alat perang lapangan masih juga dalam keadaan sangat sederhana, meriam-meriam berat, sementara itu, telah berkali-kali menggempur merusak tembok-tembok puri ksatria feodal, dan meramalkan kepada bangsawan feodal bahwa bahan peledak menentukan nasib kekuasaannya.
Tersebarnya ketrampilan mencetak, studi yang hidup kembali tentang sastra kuno, seluruh gerakan kebudayaan, yang telah menghimpun tenaga dan menjadi makin lebih umum sejak tahun 1450-ini semua adalah baik bagi burjuasi dan bagi raja dalam perjuangan mereka melawan feodalisme.
Pengaruh yang meningkat dari berbagai sebab ini, yang meningkat dari tahun ke tahun melalui aksi timbal-balik mereka yang meluas terhadap satu dengan lainnya mendorong mereka makin hebat ke arah yang sama, menentukan kemenangan atas feodalisme dalam paruh terakhir abad ke limabelas jika tidak masih untuk kaum warga kota, ya untuk monarkhi. Di manapun di Eropa, termasuk daerah-daerah terpencil yang tidak melalui tingkat feodalisme, kekuasaan raja dengan tiba-tiba memperoleh singgasana kemenangan. Di Semenanjung Iberia dua golongan Romawi setempat bergabung ke dalam sebuah kerajaan Spanyol dan negara Aragon yang berbicara Provenca dikalahkan oleh lidah sastra Kastilia; golongan ketiga menyatukan daerah bahasanya, terkecuali Galisia, ke dalam kerajaan Portugal. Belanda-nya Iberia, memalingkan punggungnya terhadap daerah pedalaman, dan menguatkan haknya untuk suatu kehidupan terpisah melalui kegiatan-kegiatan maritim.
Di Perancis Louis XI pada akhirnya berhasil, sesudah jatuhnya negara penyangga Burgundia,5) menegakkan kesatuan nasional, yang terjelma dalam kekuasaan kerajaan yang pada saat itu masih meliputi suatu wilayah terbatas dari Perancis, dan sampai pada suatu derajat sedemikian rupa sehingga penggantinya dapat ikut campur urusan Italia, dan kesatuan ini hanya pernah suatu ketika dalam waktu yang pendek terancam oleh Reformasi.6)
Inggris pada akhirnya menghentikan peperangan-peperangannya yang seperti Don Kisot itu untuk merebut wilayah-wilayah Perancis, yang lama-kelamaan toh akan menghabiskan tenaganya juga; bangsawan feodalnya mencoba menggantinya dengan Perang Bunga Mawar,7) dan memperoleh lebih banyak daripada apa yang diharapkan darinya. Ia menghabisi dirinya sendiri dan menempatkan keluarga bangsawan Tudor ke singgasana, yang kekuasaannya melampaui kekuasaan semua pendahulu dan penggantinya. Negeri-negeri Skandinavia sejak lama sudah dipersatukan, Polandia, dengan monarkhi yang sampai pada saat itu belum menjadi lemah, mendekati puncaknya sesudah persatuannya dengan Lituania, dan bahkan di Rusia juga penggulingan pangeran-pangeran penerima tunjangan raja dan pembebasan dari tindasan Tatar berlangsung bergandengan tangan dan pada akhirnya diresmikan oleh Ivan III. Di seluruh Eropa hanya terdapat dua negeri-Italia dan Jerman-di mana kerajaan dan kesatuan nasional yang pada masa itu tidak mungkin tanpa itu, atau tidak ada sama sekali, atau hanya ada di atas kertas saja.
Catatan:
1) Judul ini dibubuhkan oleh penerbit, yaitu Balai Penerbitan Bahasa Asing Moskow, sedang dalam manuskrip Engels sendiri tidak dicantumkan apa-apa.
2) Spruner-Menke, Hand-Atlas fur die Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit, 3. Aufl., Gotha 1874, Karte No. 32.
3) Ludwigslied-Sebuah hikayat tentang raja Frangkonia Barat, Ludwig III (dari dinasti Karolinga), dan tentang kemenangannya atas orang-orang Norman dalam tahun 881, direkam dalam dialek-bahasa Frangkonia-Rhein.
4) Orang-orang Slav Elbe-Suku-suku dan nasionalitas-nasionalitas Slav di sebelah timur sungai Elbe; ditaklukkan oleh tuan-tuan feodal Jerman (abad X-XIV) dengan cara yang paling buas, termasuk pembinasaan sepenuhnya atas beberapa suku Slav; yang masih hidup dijadikan hamba dan di-Jerman-kan dengan paksa.
5) Negeri Duche Burgundia-berantakan sesudah matinya Karel Pemberani pada tahun 1477; suatu bagian besar dari milik-milik Burgundia menjadi bagian dari kerajaan Perancis, dan sisanya (Nederland, dsb.) jatuh ke tangan kaum Hapsburg. Duc adalah gelar bangsawan tinggi di Eropa, dalam bahasa Belanda dinamakan hertog, sedang duche adalah wilayah yang dikuasai oleh seorang duc.
6) Yang dimaksud adalah gerakan kaum Hugenot, kaum Calvinis Perancis yang menganjurkan reformasi atau penyusunan kembali keagamaan. Gerakan itu ditindas dalam apa yang dinamakan Perang (keagamaan) Hugenot (1562-94).
7) Perang Bunga Mawar-The Wars of The Roses, suatu perjuangan membencanakan antar-dinasti antara Keluarga-bangsawan Lancaster dengan York, yang mengucilkan Inggris dalam abad ke-15, mulai dari pertempuran pertama Santa Albans (1455) sampai pertempuran Bosworth (1485).
ooo0ooo
ooo0ooo
Read More..
statement trading

ini adalah hasil live trading EA saya.hasil trading 10% tiap bulan untuk posisi aman, bisa smpe 20-30% untuk posisi spekulasi.jika ada yg berminat contact saya di 085649238006.
DAFTAR ROBO FOREX, GRATIS $15
masukkan kode referal:" ybu " jika keberatan silahkan dikosongin aja
MARKETIVA
SIGNAL FOREX HARI INI
payooner
ini adalah perusahaan yang menjual produk ksehatan.dengan daftar disini,kita akan dapat kartu kredit payooner gratis langsung di kirim kerumah kita.silahkan mencoba saya sudah mendapatkan kiriman kartu kreditnya.kegunaan kartu kredit tersebut dapat kita gunakan untuk mengaktifkan rekening paypal. silahkan klik dibawah ini.


Minggu, 13 Juni 2010
MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI INDONESIA
Artikel - Th. II - No. 6 - September 2003]
Siswono Yudho Husodo
MEMBANGUN KEMANDIRIAN DI BIDANG PANGAN:
SUATU KEBUTUHAN BAGI INDONESIA
Pada waktu ini, negara kita Indonesia menghadapi masalah yang sangat berat, antara lain :
- Pengangguran yang tinggi yang lebih dari 32 juta angkatan kerja
- Pertumbuhan ekonomi yang rendah yang hanya 2 – 3%/tahun, yang setiap 1% pertambahan ekonomi menyediakan lapangan kerja baru ± 400.000 tenaga kerja, sementara pertambahan angkatan kerja baru di Indonesia 2,5 juta orang setiap tahunnya.
- Merajalelanya korupsi di berbagai tingkatan dan di berbagai daerah.
- Terjadinya konspirasi antara pelanggar hukum dan penguasa di berbagai tempat, seperti antara penyelenggara judi dengan aparat hukum, antara terpidana dengan aparat penegak hukum.
- Besarnya energi Pemerintahan dan masyarakat yang terkuras untuk masalah politik.
- Maraknya money politic dalam berbagai proses politik.
- Meluasnya kriminalitas dan terorisme serta konflik-konflik horizontal.
- Berkembangnya etno-centrisme, fanatisme dan radikalisme.
- Kebutuhan pangan bagi rakyat yang semakin tergantung dari import dengan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi.
Masalah-masalah yang dihadapi negara kita itu bukanlah yang pertama kali terjadi di dunia ini. Masalah-masalah yang terjadi di negara kita itu telah pernah dialami oleh banyak negara lain dan banyak yang dapat mengatasinya dengan sukses.
Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara tersebut untuk mengatasi berbagai masalah tadi, dan sebagai bangsa dengan budaya paternalistik, masalahnya bisa menjadi lebih sederhana jika hadir pemimpin yang dapat memberi suri ketauladanan.
Saat di setiap pemukiman perlu tersedia, dalam jumlah yang cukup, dengan mutu yang layak, aman dikonsumsi dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
Sejak beberapa tahun terakhir ini, muncul kerisauan atas menurunnya kemampuan kita untuk memenuhi sendiri kebutuhan pangan bagi rakyat Indonesia. Dunia pun diliputi kekhawatiran itu, karena penduduk bertambah menurut deret ukur sedangkan produksi pangan bertambah menurut deret hitung. Menurut FAO, pada waktu ini di dunia terdapat ± 200 juta orang kekurangan pangan.
Penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi 2 kali lipat dan jumlahnya sekarang, menjadi ± 400 juta jiwa. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terjadi pula peningkatan konsumsi/kapita untuk berbagai pangan. Akibatnya, dalam waktu 35 tahun yang akan datang Indonesia memerlukan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali jumlah kebutuhan saat ini.
Penduduk Indonesia 1900 - 2035
Tahun
Jumlah
1900
1930
1960
1990
2000
2035
40 juta
60 juta
95 juta
180 juta
210 juta
400 juta
Diawal abad ke 20, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah 20 juta jiwa, dan diawal abad 21, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah hampir 200 juta jiwa. Penduduk Indonesia menjadi 5 kali lipat dalam waktu 100 tahun.
Pada waktu ini, rata-rata konsumsi pangan per kapita per tahun rakyat Indonesia untuk beberapa pangan penting adalah sebagai berikut:
1.Beras 133 kg (tertinggi di dunia)
2.Jagung 5,93 kg
3.Ikan 12,5 kg (rata-rata dunia 16 kg)
4.Ayam 3,8 kg (Malaysia 23 kg, Filipina 4 kg, Thailand 16,8 kg, Vietnam 1 kg) Indonesia berpotensi bertambah 2 kg dalam waktu 5 tahun yang akan datang, yang berarti tambahan kebutuhan 400 juta kg/tahun.
5.Daging 7,10 kg
6.Telur 52 butir (Malaysia 300 butir, Filipina 70 butir, Thailand 100 butir, Vietnam 40 butir) Indonesia berpotensi bertambah 10 butir dalam waktu 5 tahun yang akan datang, yang berarti tambahan kebutuhan 2 milyard butir/tahun
7.Susu 6,50 kg
8.Ketela pohon 9,93 kg
9.Buah-buahan 40,06 Kg (Jepang 120 kg, rekomendasi FAO 65,75 kg, Amerika 75 kg)
10.Gula 15,6 kg (rata-rata dunia 25,1 kg)
11.Kedelai 6,01 kg (rata-rata dunia 7 kg)
12.Sayur-sayuran 37,94 kg (rekomendasi FAO 65,75 kg, Amerika 95 kg)
Konsumsi Daging, Telur dan Susu beberapa Negara
No.
Negara
Konsumsi (Kg/Kap/Thn)
Daging
Telur
Susu
1
2
3
4
5
6
7
Indonesia
Bangladesh
China
Japan
Malaysia
Philippines
Thailand
7,10
3,08
39,00
25,97
46,87
24,96
25
3,48
0,68
10,1
20,54
17,62
4,51
9,15
6,50
31,55
2,96
10,72
3,82
0,25
2,04
(Sumber: HKTI, diolah dari berbagai sumber)
Kecuali beras, untuk pangan yang lain konsumsi/kapita/tahun rakyat Indonesia masih rendah, dan berpotensi meningkat dengan meningkatnya pendidikan, pengetahuan akan gizi dan kesejahteraan rakyat, yang akan menuntut peningkatan penyediaan pangan yang amat besar. Kedepan, akan terjadi lonjakan kebutuhan pangan yang amat besar. Pasar pangan amat besar yang kita miliki perlu kita gunakan untuk memperkuat pertanian kita, Jika salah penanganan, pasar pangan amat besar yang kita miliki itu, akan dimanfaatkan dengan baik sebagai pasar yang empuk oleh produser pangan dan luar.
Inilah hal pertama yang ingin saya sampaikan. Membahas masalah pangan bagi negara dengan penduduk yang demikian besar seperti negara kita, berarti membahas masalah sangat penting dari masa depan negara kita. Pada waktu ini, untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk yang jumlahnya ± 200 juta jiwa, setiap tahunnya Indonesia sebaqai negara agraris, harus mengimpor, jagung lebih dari 1 juta ton, kacang tanah ± 0,8 juta ton, kacang hijau ± 0,3 juta ton, dan gaplek ± 0,9 juta ton.
Import beras di tahun 1998, sebesar 5,8 juta ton, dan 4 juta ton pada tahun 1999 serta rata-rata 2 juta ton/tahun, telah menjadikan Indonesia importir beras terbesar di dunia, padahal 14 tahun sebelumnya, kita telah mampu berswasembada beras. Impor biji kedelai pada lima tahun terakhir rata-rata 0,8 juta ton pertahun senilai US$ 226,838 juta setara Rp. 2,3 Triliun (1 US$ = Rp. 10.000,-) padahal hanya 15 tahun sebelumnya kita mampu berswasembada. Produksi kedelai dalam negeri terus menurun 0,81%/tahun, sementara kebutuhan terus meningkat 2,41%/tahun, dari 2.312.000 ton di tahun 1998, menjadi 2.737.000 ton di tahun 2005. Dengan import kedelai 1.156.058 ton di tahun 1999, senilai US$ 254 juta, menjadikan Indonesia importir kedele untuk pangan manusia terbesar di dunia. Luas areal tanaman kedelai tahun 1992 adalah 1,67 juta Ha, turun tinggal 0,8 juta Ha (separuhnya) di tahun 2000, karena membanjirnya kedelai import yang murah. Di tahun 2000 import kedelai meningkat menjadi Rp 4,7 Triliun.
Pada waktu ini, bea masuk kedelai 0%, dengan harga ± Rp. 1.500,- - Rp. 1.600,-/kg, sangat memukul petani karena biaya produksi kedelai dalam negeri Rp. 2.100,- - Rp. 2.200,-/kg. Sebaiknya, Pemerintah mengenakan bea masuk kedelai 50% agar terbentuk harga di pasar sekitar Rp. 2.500,-/kg. Harga komoditas pertanian yang rendah, disincentive bagi peningkatan produksi.
Produksi gabah/beras pada tahun 2001 = 50,18 juta ton GKG setana dengan 29,8 juta ton beras, turun sekitar 3,31 pensen dari produksi tahun sebelumnya (51,89 juta ton GKG). Selain gabah/beras dan kedelai, komoditas pangan lainnya (jagung, kacang tanah, ubi jalar, dan ubi kayu) dalam tahun 2001 mengalami penurunan. Hanya kacang hijau yang produksinya mengalami peningkatan dibanding tahun 2000.
Produksi Padi dan Palawija Tahun 2000 dan Perkiraan Tahun 2001 (Juta Ton)
Komoditas
2000
2001
Perubahan (%)
Padi (GKG)
51,89
50,18
-3,31
Jagung
9,67
9,29
-3,92
Kedelai
0,73
0,92
-9,27
Kacang tanah
1,01
0,70
-3,66
Kacang hijau
0,28
0,34
20,41
Ubi jalar
1,82
1,61
-11,90
Ubi kayu
16,08
15,60
-3,01
Sumber : BPS, Angka Ramalan II Tahun 2001
Penyebab utama penurunan produksi adalah karena tidak adanya rangsangan untuk meningkatkan produksi, karena rendahnya harga. Selama 6 kali panen sejak tahun 1998, harga beras juga kedelai terus tertekan amat rendah. Perlu pula kita cermati bahwa masyarakat kita akhir-akhir ini, dengan kecepatan yang meningkat semakin banyak mengkonsumsi roti dan mie, yang bahan bakunya gandum, bahan makanan yang belum dapat kita produksi sendiri. Jenis-jenis makanan Eropa/Amerika berupa roti, hamburger, serta makanan Jepang, kuat sekali merasuk ke masyarakat kita khususnya golongan berpenghasilan tinggi. Akibatnya, sejak tahun 1996 setiap tahun kita mengimport gandum 4,5 juta ton.
Selama 5 tahun terakhir, rata-rata setiap tahun kita mengimport gula 1,6 juta ton, menjadikan Indonesia importir gula no. 2 terbesar di dunia setelah Rusia, padahal semasa penjajahan Belanda kita adalah exportir gula terbesar No. 2 di dunia. Sekarang kita import sapi ± 400.000 ekor/tahun, merupakan negara tujuan export sapi Australia yang terbesar, padahal di tahun 70-an, kita masih menjadi exportir sapi. Di Western Australia sekarang ini sedang dipersiapkan peternakan kambing secara besar-besaran yang studinya menyebutkan untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia.
Pada waktu ini, Indonesia merupakan negara pengimpor pangan yang amat besar. Di tahun 2000, impor Indonesia atas delapan komoditas pangan yaitu gandum, jagung, beras, biji dan bungkil kedelai, kacang tanah, gula pasir dan bawang putih, mencapai nilai Rp 16,62 triliun.
Volume dan Nilai Impor Delapan Komoditas Pangan Tahun 2000
No
Komoditas
Volume
(ton)
Nilai
(dolar AS)
1
Gandum
3.576.665
500.312.470
2
Jagung
1.236.764
150.012.707
3
Beras
550.514
131.132.613
4
Biji kedelai
1.277.685
275.481.226
5
Bungkil kedelai
1.262.040
268.746.270
6
Kacang tanah
111.284
35.601.776
7
Gula pasir
1.680.275
290.873.225
8
Bawang Putih
174.702
44.120.000
J u m l a h
9.869.929
1.696.280.287
Dengan kurs Rp 9,800,- per dolar AS, nilai komoditas itu setara dengan Rp 16,62 triliun.
Sumber: HKTI, diolah dari berbagai sumber
Disamping itu, menurut BPS, impor Indonesia tahun 2000 atas buah segar seperti: apel volume impornya 73.426 ton dengan nilai 42,42 juta dolar AS, jeruk 19.438 ton dengan nilai 10,8 juta dolar AS, jeruk mandarin 58.423 ton dengan nilai 30,04 juta dolar AS. Impor Indonesia atas sayuran seperti: bawang 13.358 ton dengan nilai 3,4 juta dolar AS, dan kentang 4.569 ton dengan nilai 1,4 juta dolar AS. Import pangan dirangsang oleh pertama, kebutuhan dalam negeri yang amat besar; kedua, harga di pasar international yang rendah, ketiga, produksi dalam negeri yang tidak mencukupi; dan keempat, adanya bantuan kredit impor dari negara eksportir.
Harga di pasar International yang rendah, terbentuk oleh hadirnya residual goods (bahan-bahan yang harganya sangat murah karena di negara produsernya tidak laku dijual, seperti paha ayam dari Amerika Serikat dan jerohan ternak dari Australia serta kelebihan produksi yang melimpah dari negara-negara produsen yang dilempar keluar negerinya, agar harga di dalam negerinya tetap tinggi, seperti gula dari Australia yang di pasar dalam negeri Australia harganya Rp. 5.000,-/kg; kelebihan produksinya di lempar ke Indonesia dengan harga Rp. 2.100,-/kg; juga gula India, beras Thailand, beras Vietnam, tembakau Cina, jeruk Cina dari Taiwan dan lain-lain) yang telah ikut rnenghancurkan pertanian Indonesia.
Pada tahun ini, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA - United State Departement of Agriculture) memberikan bantuan kredit melalui GSM-108, senilai 650 juta dollar AS dengan bunga yang sangat rendah kepada para importir Indonesia untuk mengimport produk pertanian Amerika Serikat terutama kedelai, jagung, gandum dan beras. Pengembalian kredit ini sangat ringan dan dalam jangka panjang. Para importir sangat menikmati fasilitas ini, karena sebelum kredit dikembalikan, para importir dapat memanfaatkannya terlebih dahulu. Kondisi ini juga membuat banyak pihak tidak ingin melihat kita membangun kemandirian di bidang pangan, dan telah ikut menjadi penyebab merosotnya produk-produk pertanian kita.
Negara-negara maju dalam membantu negara-negara berkembang, juga mementingkan kepentingan nasionalnya. Amerika memberi kredit pangan, membantu petaninya agar semakin kuat, Presiden George Bush baru saja mengesahkan Act baru yang memberi plafond subsidi untuk pertanian Amenika sebesar 82 milyard US$ dalam 10 tahun. Jepang membantu pembangunan jalan. Agar mobil-mobil Jepang lebih banyak terjual.
Tanpa perencanaan yang matang dan langkah-langkah strategis yang konsisten untuk meningkatkan produksi pangan, Indonesia sebagal negara agraris dalam anti mayoritas angkatan kerjanya bekerja di bidang pertanian, akan terus menjadi negara “nett importir” pangan yang sangat besar, yang akan terus semakin membesar, yang pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional kita.
Inilah hal kedua yang ingin saya nyatakan, yaitu bahwa negara-negara maju dalam membantu negara-negara berkembang, mengutamakan memperkuat basis perekonomiannya sendiri; antara lain memperkuat petaninya.
Kita memang hidup di dunia yang oleh banyak orang disebut “The Borderless World”, dunia yang tanpa batas, dengan arus barang, orang, modal dan uang serta teknologi dan budaya yang hampir-hampir tanpa hambatan, sehingga masalah import pangan bukanlah sesuatu yang harus ditabukan. Tetapi karena penduduk kita banyak dan potensinya ada, sebaiknyalah kita mampu memenuhi sendiri kebutuhan pangan kita. Kita harus semakin cerdik hidup di “ The Borderless World” ini.
Sampai dengan tahun 1970-an, banyak tulisan dari pakar memperkirakan bahwa masa depan pangan dunia akan dapat dipenuhi dari negara-negara dunia ketiga, di antaranya Brazilia, Argentina, India, China juga Australia dan Indonesia karena wilayahnya yang luas, sementara negara-negara maju akan lebih mengkonsentnasikan diri pada industri maju berteknologi tinggi, yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Tetapi sejak akhir tahun 1980-an, dengan ditemukannya teknologi kloning untuk ternak, bioteknologi rekayasa genetika (Organisme Hasil Modifikasi-OHM), dunia kembali berharap bahwa kebutuhan pangan masa depan dunia akan datang dari negara-negara maju.
Jika harga pangan di pasar dunia semakin murah (yang disebabkan oleh banjirnya residual goods, barang-barang kelebihan dari negara-negara produser yang dilempar ke pasar internasional seraya menjaga harga di dalam negerinya yang tinggi), negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia akan semakin tergantung pada pangan impor dan upaya membangun kemandirian pangan semakin sulit. Instrument yang tersedia dan diperbolehkan oleh aturan-aturan WTO untuk menghambat impor adalah tariff bea masuk. Sebagai contoh biaya produksi 1 Kg ayam hidup di Indonesia adalah ± Rp 6.500,- dan ini termurah di Asean. Ayam potong menjadi ± Rp 9.500,-/Kg sementara paha ayam Amerika di negerinya tidak dimakan orang, dijual di Jakarta Rp 4.500,-/Kg. Biaya produksi gula di Indonesia ± Rp 2.300,-/Kg. Sementara gula import ex Australia masuk Tanjung Priok dengan harag Rp 1.700,-/Kg, tetapi harga di pasar-pasar Canbera ± Rp 4.500,-Kg. Beras Thailand seharga US $ 160/ton atau ± Rp 1.550,-/Kg. Berhadapan dengan biaya produksi di Indonesia ± Rp 2.300,-/Kg, tetapi harga beras di Bangkok ± Rp 3.800,-/Kg. Thailand setiap tahun surplus beras ± 2 juta ton. Ini disebut residual trading.
Perlu disadari oleh semua pihak, petani, masyarakat luas, pemerintah dan Lembaga Legislatif bahwa :
- Kemampuan kita disbanding pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, relatif telah dan sedang menurun dengan sangat besar.
- Pada waktu ini Indonesia berada dalam keadaan “Rawan Pangan” bukan karena tidak adanya pangan, tetapi karena pangan untuk rakyat Indonesia sudah tergantung dari supply luar negeri, dan ketergantungannya semakin besar.
- Pasar pangan amat besar yang kita miliki diincar oleh produsen pangan luar negeri yang tidak menginginkan Indonesia memiliki kemandirian di bidang pangan
Inilah kesimpulan yang ingin saya nyatakan mengenai kondisi pangan kita pada waktu ini. Bagian berikut menyangkut masa depan pangan kita.
Pada tahun 2035, dengan jumlah penduduk sebanyak ± 400 juta jiwa, kebutuhan beberapa jenis pangan untuk Indonesia setiap tahunnya diperkirakan :
No
Jenis
Konsumsi/Kapita/th
Tahun 2035
Kebutuhan Nasional Tahun 2035
Produksi dalam Negeri Tahun 2001
Keterangan
1
Beras
90 Kg (turun 30%)
36 juta ton
29 juta ton
+ 25%
2
Daging (ayam,sapi,dll)
15 Kg (naik 2 X)
6 juta ton
2,2 juta ton
3 Kali
3
Telur
90 Butir (naik 3 X, masih di bawah Malaysia
36 M butir
12,6 M butir
3 Kali
4
Susu
12 liter
4,8 M liter
1,2 M butir
4 Kali
5
Gula
25 Kg
10 juta ton
1,9 juta ton
5 Kali
6
Ayam
8 Kg
3,2 juta ton
750 ribu ton
4 Kali
Tampak bahwa kebutuhan beberapa jenis pangan untuk rakyat Indonesia di tahun 2035, sangat besar bila dibandingkan dengan kemampuan produksi kita pada waktu ini. Diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang memadai untuk memenuhi tuntutan produksi yang begitu besar itu, bila kita ingin mandiri di bidang pangan.
Pertanyaan awalnya adalah, apakah kita ingin dapat memenuhi sendiri kebutuhan pangan yang begitu besar itu. Kalau ingin apakah mampu dan caranya bagaimana ?
Mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia, dan karena tersedia lahan yang cukup luas dan tenaga kerja pertanian yang cukup banyak, serta begitu besarnya devisa yang terkuras untuk impor pangan, dan mengingat sangat terbatasnya devisa yang kita miliki, dan kebutuhan negara yang sangat besar untuk membayar bunga dan cicilan hutang (luar negeri) hampir 150M $ terbesar No. 4 di dunia, Indonesia perlu berusaha semaksimal mungkin MENCUKUPI KEBUTUHAN PANGANNYA SECARA MANDIRI, dalam waktu yang tidak terlalu tama (± 10 tahun). Hal ini sepatutnya menjadi keputusan politik negara. Diperlukan upaya khusus untuk sampai pada keputusan potitik ini.
Mandiri dalam bidang pangan dalam arti kita mampu memproduksi sendiri produk-produk pertanian/pangan yang kita butuhkan dengan dukungan unsur-unsur pendukungnya (benih, alsintan, pupuk, obat-obatan dan lain-lain) yang dapat kita sediakan sendiri. Selanjutnya menjadi negara exportir pangan. Kemandirian di bidang pangan lebih dari sekedar swasembada yang dapat didukung oleh alsintan, pupuk dan obat-obatan import seperti yang telah pernah kita capai di tahun 1984, tetapi dengan dukungan traktor, pupuk, benih, obat-obatan made in Indonesia.
Bukan hanya di bidang pangan, secara umum bangsa yang berpenduduk sangat banyak, 210 juta jiwa, no 4 terbanyak di dunia ini, harus segera dapat membangun kemandirian ekonominya, agar Indonesia mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi bangsa ini. Tap MPR RI No II/MPR/2002 dan Tap MPR RI No. VI/MPR/2002 telah juga mengamanatkan hal tersebut. UUD 1945 perubahan ke ernpat juga telah menetapkan kemandirian sebagai salah satu prinsip pembangunan ekonomi Indonesia. Proklamator kemerdekaan Indonesia Bung Karno, dalam semangat kemandirian itu menganjurkan kita melaksanakan Tri Sakti yaitu : berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Sementara itu, meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat membuat masyarakat menuntut kwalitas pangan yang lebih bergizi, lebih enak, lebih higienis dan lebih aman. Dunia juga menuntut pangan yang lebih berkwalitas.
Pada waktu ini, banyak export pangan kita yang ditolak FDA dari USA, dan menjadikan harga export produk-produk pertanian dan pangan kita harganya tertekan. Pada waktu yang akan datang, peningkatan kwalitas produk pertanian dan pangan perlu memperoleh perhatian yang memadai. Begitu besar tantangan yang dihadapi di bidang produksi pangan, yaitu peningkatan volume produksi, peningkatan kwalitas produk dan penganekaragaman produk serta meningkatkan daya saingnya.
Secara umum di bidang pertanian, juga peternakan dan perikanan diperlukan perubahan-perubahan yang mendasar, terutama dengan meningkatkan skala usaha petani, perikanan dan peternakan kita, menjadikan setiap usaha tani, usaha peternakan dan usaha perikanan mencapai skala ekonomi yang dapat membuat pelakunya sejahtera.
Hal ini adalah suatu keharusan, kalau kita ingin membuat petani, peternak dan nelayan kita sejahtera, membuat produksinya berdaya saing tinggi, serta ingin membangun kemandirian di bidang-bidang itu. Perluasan lahan usaha per KK petani merupakan persyaratan utama.
Ada beberapa permasalahan mendasar yang perlu memperoleh penanganan serius dalam upaya kila membangun kemandirian di bidang pangan:
Pertama, semakin mengecilnya rata-rata penguasaan lahan pertanian per KK petani, dari 0,93 hektar pada tahun 1983, menjadi 0,83 hektar pada tahun 1993. Di luar Pulau Jawa menurun dari 1,38 hektar menjadi 1,19 hektar, dan di Pulau Jawa menurun dari 0,58 hektar menjadi 0,47 hektar, sekarang diperkirakan 0,3 Ha. Sebagian besar (43 persen RTP) merupakan kelompok tunakisma atau petani yang memiliki lahan pertanian kurang dari 0,1 ha.
Struktur Penguasaan Tanah Pertanian di Indonesia (1993)
No
Kelompok Luasan
Penguasaan (Ha)
Rumah Tangga Petani
%
%
Kumulatif
% LuasTanah
Yang Dikuasai
1
Tunakisma dan
petani kurang 0,1
43
43
13
2
0,1 - 0,49
27
70
18
3
0,5 - 0,99
14
84
4
>1,0
16
100
69
Sumber : Sensus Pertanian Indonesia, Tahun 1993
Semakin mengecilnya rata-rata penguasaan lahan pertanian oleh RTP tersebut disebabkan oleh terjadinya fragmentasi pemilikan, bertambahnya jumlah petani dan karena alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Berdasarkan data dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah terjadi alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian di Pulau Jawa untuk permukiman dan industri antara tahun 1994 - 1999, seluas 81.176 hektar terdiri dari permukiman seluas 33.429 hektar dan industri seluas 47.747 hektar. Alih fungsi tanah pertanian tersebut yang terluas di Jawa Barat (79,41 persen), Jawa Timur (17,01 persen), Jawa Tengah (2,69 persen), cukup kecil dan Daerah Istimewa Yogyakanta (0,89 persen).
Teman saya seorang petani Belanda menyatakan bahwa sebelum PD II, rata-rata petani Belanda menggarap lahan seluas 14 Ha. Pada waktu ini, dengan berkurangnya jumlah petani (adanya perluasan areal pertanian di polder-polder baru, rata-rata petani Belanda menggarap 75 Ha, dengan mekanisasi yang semakin canggih, menjadikan Negeri Belanda yang tanahnya sempit itu, exportir hasil pertanian yang terbesar di Eropa. Di Negeri Belanda, lahan pertanian tidak boleh dibagi untuk diwariskan. Dia juga menyatakan bahwa daya saing sangat tinggi yang dimiliki petani Belanda terjadi karena lahan usaha petani yang terus semakin luas, yang telah mendorong meningkatkan mekanisasi yang semakin maju.
Kedua, semakin bertambahnya jumlah rumah tangga petani (RTP) yang menguasai lahan di bawah 0,5 hektar. Pada tahun 1983, jumlah petani gurem 9,53 juta RTP, dan sepuluh tahun kemudia’ (1993) meningkat menjadi 10,94 juta RTP, di mana 74 persen di antaranya berada di PuIa Jawa. Angka statistik tersebut menunjukkan, bahwa dalam jangka waktu sepuluh tahun terdapat penambahan 1,41 juta RTP gurem.
Kedua hal ini, yaitu menyempitnya lahan pengusahaan petani dan meningkatnya jumlah petani gurem, merupakan hambatan besar bagi upaya peningkatan produktivitas dan kwalitas hasil pentanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Membiarkan proses fragmentasi lahan berlangsung terus, akan membuahkan petani dan peternak yang semakin miskin, juga akan membuat produk-produk pertanian dan peternakan kita tidak memiliki daya saing yang tinggi baik dari segi kwalitas maupun harga. Dengan membiarkan hal itu, kita tidak akan pernah mampu memenuhi sendiri kebutuhan pangan kita.
Inilah hal pertama yang ingin saya nyatakan tentang masa depan pangan kita.
Ketiga, rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) apabila dibandingkan dengan Nilai Tukar Industri atau lainnya. Hal itu semakin mempersulit kehidupan petani dan menurunkan motivasi petani dalam berusaha tani. Kebijakan harga pangan murah yang telah berlangsung lama, sangat merugikan petani. Dengan harga pangan yang murah, upah buruh menjadi murah dan inilah salah satu daya tarik investasi. Terkesan terjadi subsidi terselubung dari sektor pertanian kepada sektor industri.
Pemerintah Pusat dan Daerah perlu membantu upaya perluasan lahan pengusahaan per KK petani lengan memberi kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan-lahan negara. Pemerintah Pusat dan Daerah yang wilayahnya luas perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk perluasan areal pertanian di lahan kering. Perluasan areal pertanian di lahan kering relatif lebih murah, sekitar Rp 4 Juta/ha, dibanding dengan investasi lahan sawah beririgasi yang ± Rp 12 juta/Ha. Di era otonomi daerah ini kemampuan daerah-daerah untuk mewujudkan perluasan areal pertanian dan perluasan lahan pengusahaan petani tidaklah sama. Propinsi-Propinsi yang luas dan kaya seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Jambi, Sumatera Selatan dapat segera mengembangkan pertanian dan peternakan yang luas milik petani dengan mekanisasi. Jumlah petani juga perlu berkurang dengan alih profesi yang direncarakan dan dipersiapkan.
Ketahanan pangan yang terlalu bergantung pada satu komoditi beras, mengandung resiko bahwa kebutuhan pangan rumah tangga dan nasional akan rapuh. Oleh karenanya, ke depan kita perlu meningkatkan upaya pengembangan pangan alternatif yang berbasis umbi-umbian (ubi, ketela, garut, dll), tanaman pohon (sukun dan sagu), serta bahan pangan berbasis biji-bijian (beras, jagung, sorgum, dli), yang dapat diproses menjadi tepung yang bisa diolah menjadi aneka produk makanan yang mempunyai nilai tambah tinggi. Di Thailand, makanan berbasis tepung singkong variasinya banyak sekali.
Masyarakat kita perlu mengembangkan makanan berbasis tepung, yang bisa tahan lebih lama, dapat diperkaya dengan mineral dan vitamin, serta lebih fleksibel pengolahannya. Mengembangkan bahan pangan tepung tidak harus berupa industri besar, sebab jagung atau beras dapat ditumbuk atau digiling dengan mesin giling tepung yang tersebar di desa-desa penghasilnya, sementara untuk membuat tepung sagu, teknologinya telah dikuasai masyarakat lokal. Sayangnya teknologi pemanfaatan tepung dan bahan yang dapat kita produksi sendiri seperti tepung tapioka, tepung beras, tepung jagung, tepung sagu belum berkembang dengan baik untuk menjadi bahan baku roti, pengganti gandum. Penggunaan yang umum baru pada produk kueh/makanan ringan.
Sekalipun potensi bahan pangan alternatif yang kita miliki cukup besar dan beragam, tetapi dalam pengembangannya bukanlah perkara mudah. Kita dihadapkan pada berbagai kendala yang cukup mendasar. Di samping kendala teknis dan pembiayaan, ada juga kendala budaya sosial dan psikoiogis berupa pandangan bahwa beras merupakan makanan bergengsi (superior food) sedang umbi-umbian, sagu, sukun, jagung, dll merupakan makanan inferior (inferior food), sementara gandum bukan makanan yang dapat kita produksi sendit.
Masyarakat luas bersama Pemerintah perlu pula terus menerus melaksanakan sosialisasi dan kampanye diversifikasi pangan, disertai bimbingan teknis dan insentive ekonomi dari pangan pokok beras kepada pangan pokok lokal lainnya, atau dengan campuran untuk mengurangi konsumsi beras antara lain dengan beras jagung, sagu, jagung, ubi dan lain-lain. Penggantian 10% kebutuhan pangan yang semula beras ( setara ± 3,1 juta ton/tahun) dengan pangan selain beras, akan membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor beras.
FAO (Food and Agriculture Organization) melalui siaran persnya nomor 00/43, menyebutkan antara lain:
Dalam waktu 30 tahun yang akan datang, peningkatan produksi pangan akan lebih besar daripada pertambahan penduduk. Peningkatan produksi yang tinggi itu terjadi di negara maju. Kecukupan pangan dan kwalitas makanan akan membaik, tetapi jumlah penduduk dunia yang kekurangan pangan meningkat.
Produksi hasil-hasil pertanian dunia meningkat semakin melandai, dari 2,1%/tahun selama 20 tahun terakhir, menjadi 1,6%/tahun antara tahun 2000 - 2015 dan menjadi 1,3%/tahun antara tahun 2015 - 2030, sementara pertambahan penduduk dunia antara tahun 2000 - 2015 sebesar 1,2%/tahun dan 0,8% diantara tahun 2015 - 2030. Dengan jumlah penduduk mencapai 8 miliar di tahun 2030, kekurangan pangan tetap akan mengancam dunia. Di tahun 2015 diperkirakan 580 juta penduduk dunia akan mengalami kekurangan pangan. Makanan pokok penduduk tetap berasal dari biji-bijian, yang memasok setengah dari kalori makanan. Kebutuhan biji-bijian akan berkisar 50 persen untuk konsumsi manusia, 44 persen makanan ternak dan 6 persen industri. Negara-negara berkembang akan semakin tergantung pada bahan pangan impor.
Impor biji-bijian negara-negara berkembang akan meningkat hampir 2 kali lebih besar dalam waktu 35 tahun yang akan datang, dari 170 juta ton di tahun 1995 menjadi 270 juta ton di tahun 2030. Negara-negara yang secara tradisional merupakan exportir biji-bijian, seperti Amerika Utara, Eropa Barat, dan Australia perlu meningkatkan ekspor bahan pangannya dari 142 juta ton di tahun 1995 menjadi 280 juta ton di tahun 2030.
Bagi saya pribadi, sangatlah meresahkan membaca siaran pers FAO tersebut, di mana FAO justru mendorong sekaligus merekomendasikan negara-negara seperti Amerika Utara, Eropa Barat, dan Australia meningkatkan ekspor bahan pangannya. Mengapa FAO tidak menganjurkan membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia meningkatkan produksi pangannya. Sepatutnyalah kita menyadari bahwa negara-negara maju produsen pangan yang melimpah itu, tidak akan merelakan Indonesia memiliki kemandirian di bidang pangan.
Indonesia dengan jumlah penduduknya yang banyak, merupakan pasar pangan yang amat besar yang diincar oleh negara-negara produsen pangan. FAO dan banyak lembaga-lembaga International lain dalam membantu negara negara berkembang, sangat diwarnai oleh kepentingan negara-negara maju, sesuatu yang wajar dalam peradaban manusia yang semakin menjadi Homo Economicus.
Dengan kindisi daya saing pertanian Indonesia saat ini liberalisasi perdagangan ASEAN yang akan diwujudkan dalam Asean Free Trade Area (AFTA) tahun 2003 yang akan datang, harus dicermati sebagai bahaya besar bagi hidup matinya pertanian Indonesia. Di bidang pertanian untuk produk-produk tertentu Indonesia belum siap memasuki AFTA 2003, tanpa langkah-langkah yang tepat, belum siap menghadapi Pasar Bebas Asia Pacific 2010 dan Pasar Bebas Dunia 2020. Jika kita tidak mampu mengelola dengan baik pensaingan yang akan terjadi, maka kehancuran pertanian Indonesia akan menjadi kenyataan, yang berarti jutaan petani Indonesia akan kehilangan pekerjaan dan akibatnya pangan bagi rakyat Indonesia akan semakin tengantung dari import.
Tuntutan peradaban masyarakat dunia membawa kita pada kehidupan yang semakin liberal, semakin demokratis, dan manusia semakin menjadi homo economicus, yang menempatkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi sebagai pertimbangan utama dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karenanya, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda utama semua pemerintahan di muka bumi ini. Dan karena mayoritas rakyat Indonesia adalah petani, maka peningkatan kesejahteraan petani perlu memperoleh perhatian dari semua pihak, terutama Pemerintah. Peningkatan kesejahteraan yang terjadi atas dasar peningkatan produktivitasnya. Masyarakat menuntut kehidupan yang semakin nyaman, kwalitas hidup yang semakin baik, pelayanan yang semakin cepat; makanan yang semakin lezat, gizi yang semakin baik, keamanan pangan yang semakin tinggi, dan oleh karenanya bagi semua pelaku kegiatan ekonomi dituntut untuk menghasilkan roduk yang semakin banyak dan semakin baik, dengan pelayanan yang semakin cepat dan nyaman serta persaingan harga yang semakin ketat. Persaingan hidup antar bangsa, antar anggota masyarakat dan antar individu yang semakin tinggi tidak dapat dielakkan.
Dalam suasana yang seperti itu, yang harus kita lakukan sebagai suatu bangsa adalah terus-menerus melakukan peningkatan produktivitas dan kwalitas produk-produk kita, membangun daya saing yang semakin tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah hal ketiga yang ingin saya nyatakan tentang masa depan pangan kita. Gagasan pemerataan yang tidak didasari oleh semangat itu akan bertentangan dengan kecenderungan peradaban manusia, bertentangan dengan tuntutan kemajuan, yang akhirnya akan menyulitkan kita sendiri, menjerumuskan kita ke dalam lembah kemiskinan struktural yang sangat sulit untuk mengatasinya. Tersedia cara-cara untuk melakukri pemerataan sekaligus meningkatkan kwalitas dan produktivitas; walaupun hal itu tidaklah mudah.
Pengalaman masa lalu kita menunjukan bahwa sebagai suatu bangsa kita telah membiarkan berlangsungnya proses menyempitnya lahan pengusahaan petani kita, yang telah mengakibatkan para petani pnoduktivitasnya rendah dan menjadi miskin, sementara petani-petani di negara lain lahannya terus semakin meluas. Walaupun kita memiliki pakar yang cukup banyak di bidang gula dan memiliki pengalaman yang panjang sebagai produsen utama, kita telah membiarkan proses menurunnya tingkat produktivitas gula yang berlangsung bertahun-tahun secara bertahap. Di zaman Belanda, tingkat produktivitas gula kita 15 ton/Ha, dan sekarang tinggal 4,5 ton/Ha.
Penurunan tingkat produktivitas gula di Pulau Jawa tidak tenjadi secara mendadak, tetapi bertahap merosot terus, dan kita sekalian, Pemerintah, pabrik gula dan petani, seperti tak mampu mengerem kemerosotan itu. Zaman Belanda produksi gula 15 ton gula/ha, di akhir tahun 50 an =10 ton gula/ha, akhir tahun 60 an = 8 on gula/ha.
Selanjutnya di tahun 1975 diterbitkan Inpres IX/75, yang semakin memerosotkan produktivitas gula di P. Jawa, dan sekarang tinggal 4,5 ton gula/ha
Di waktu yang lalu, sewaktu ditemukan teknologi baru penangkapan ikan dengan trawl, kita bukannya membina nelayan untuk lebih produktf dengan menggunakan trawl, tetapi malah melarangnya dengan alasan pelestarian lingkungan. Sekarang trawl ini digunakan secara luas di Thailand, Jepang dan banyak negara lain di dunia, dan rnenjadikan nelayan kita tidak produktif mengais-ngais ikan di tepi pantai dengan peralatan yang kuno. Export ikan Thailand yang luas lautnya tidak lebih luas dari laut Jawa Tengah itu, lebih besar dari export Indonesia yang luas lautnya 5 juta Km2. Di Australia, tidak ada peternak s yang jumlah sapinya kurang dari 200 ekor.
Di Jepang orang tidak akan bertani kalau lahannya kurang dari 1 Ha. Dan lahan seluas itu digarap sangat intensif; banyak yang seluruhnya di dalam Green House. Di Belanda, lahan pertanian dilarang dibagi untuk diwariskan. Sebagai suatu egara, jangan ada kebijakan yang mendorong menurunkan prestasi produktivitas dan kwalitas. Juga di pendidikan seperti meluluskan semua peserta ujian SLTA, membiarkan tanpa hukuman siswa yang berantem dan lain-lain. Semua bangsa di negana-negara yang maju berlomba-lomba mensejahterakan warganya dengan bantuan negara, memenuhi tuntutan kemajuan peradaban manusia dengan cara-cara yang memenuhi kaidah-kaidah ekonomi, memperkuat basis ekonomi ekonomi warganya. Sangat besar subsidi negara untuk petani di Eropa. Dengan alasan yang sama, keluar pula kredit export oleh US DA untuk membantu petani Amerika. Walaupun luas laut kita 5 juta km2, dengan panjang pantai 88.000 km, no. 2 di dunia setelah Canada, dan air laut kita tetap asin, setiap tahun Indonesia mengimport garam lebih dari 1 juta ton, karena petani-petani garam tidak didorong untuk menggunakan teknologi modem, yang lebih produktif.
Agar penbangunan pertanian memiliki arah yang jelas, negara perlu menetapkan politik pertanian yaitu keputusan sangat mendasar dibidang pertanian pada tingkat negara, yang menjadi arah ke depan, untuk menjadi acuan semua pihak yang terlibat, dengan sasaran membangun kemandirian di bidang pangan. Menurut hemat saya, kalau kita ingin sukses dalam persaingan di bidang pertanian di “The Borderless World” ini, beberapa sasaran perlu ditetapkan untuk di upayakan oleh semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, petani dan masyarakat luas.
Beberapa sasaran yang penting itu adalah :
1. Perluasan areal pertanian, khususnya di lahan kering yang besarnya perlu diteliti, paling tidak 200.000 Ha/tahun, dimana 40.000 Ha untuk menggantikan areal pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian.
2. Peningkatan skala usaha petani, peternak dan nelayan; untuk petani, perluasan areal pengusahaan petani dari rata-rata 0,3 Ha/KK di tahun 2001, menjadi rata-rata 8 Ha di tahun 2030 dan mengembangkan mekanisasi.
3. Pengurangan jumlah petani baik prosentasenya terhadap angkatan kerja maupun nominalnya dari ± 48% di tahun 2001 (22,5 juta) menjadi ± 15% di tahun 2030 (15 juta). Pengurangan jumlah petani ini dapat berlangsung bila pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan penyalurannya direncanakan dan dipersiapkan dengan baik.
4. Menetapkan kebijakan yang dapat membuat harga produk pertanian di dalam negeri cukup baik, antara lain melalui tarif bea masuk, agar diperoleh rangsangan untuk peningkatan produksi. Arah kebijakan pertanian pada umumnya seharusnyalah mensejahterakan petani.
5. Menetapkan sasaran untuk dapat kembali berswasembasa beras di tahun 2006, daging sapi di tahun 2010 dan susu sapi tahun 2015.
6. Menetapkan sasaran untuk menjadi negara nett exportir pangan di tahun 2010, dengan idopsi teknologi.
7. Mengembangkan industri pertanian dan pangan yang berkwalitas tinggi, Membangun agro industri di desa.
8. Mengembangkan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal.
Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan, dengan harapan semoga bermanfaat baqi pembangunan bangsa dan negara kita, khususnya dalam membangun kemandirian di bidang pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangar agroindustri yang memiliki daya saing yang tinggi.***
Oleh: Ir. Siswono Yudho Husodo -- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
Disampaikan pada: Seminar “Kemandirian Ekonomi Nasional” diselenggarakan oleh Fraksi Utusan Golongan Jakarta, 22 November 2002
DAFTAR PUSTAKA :
1. “Sensus Pertanian 1993”, Jakarta : BPS, 1995
2. Tomich, Thomas P dan kawan-kawan, “Transforming Agrarian Economics: Opportunities Seized, Opportunities Missed”, Ithaca : Cornell University Press,1995
3. Mantra, Ida Bagus, “Mobilitas Penduduk Sekuler dari Desa ke Kota”, Yogyakarta Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1995
4. Faturochman, Marcelinus Malo “Kemiskinan dan Kependudukan di Pedesaan Jawa”, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1995
5. Djojohadikusumo, Sumitro, “Pembangunan Ekonomi Indonesia”, Jakarta : Sinar Agape Press, 1995
6. Sayogyo, “Demokrasi dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia”, Jakarta Gramedia Widiasarana, 1996
7. Soegijoko, Sugiyanto, “Bunga Rampai Pembangunan di Indonesia” Jakarta Gramedia, 1997
8. Press Release FAO No. 00/43
9. Kliping koran HKTI berita-berita pertanian 1999, 2000, 2001, 2002 Read More..
Siswono Yudho Husodo
MEMBANGUN KEMANDIRIAN DI BIDANG PANGAN:
SUATU KEBUTUHAN BAGI INDONESIA
Pada waktu ini, negara kita Indonesia menghadapi masalah yang sangat berat, antara lain :
- Pengangguran yang tinggi yang lebih dari 32 juta angkatan kerja
- Pertumbuhan ekonomi yang rendah yang hanya 2 – 3%/tahun, yang setiap 1% pertambahan ekonomi menyediakan lapangan kerja baru ± 400.000 tenaga kerja, sementara pertambahan angkatan kerja baru di Indonesia 2,5 juta orang setiap tahunnya.
- Merajalelanya korupsi di berbagai tingkatan dan di berbagai daerah.
- Terjadinya konspirasi antara pelanggar hukum dan penguasa di berbagai tempat, seperti antara penyelenggara judi dengan aparat hukum, antara terpidana dengan aparat penegak hukum.
- Besarnya energi Pemerintahan dan masyarakat yang terkuras untuk masalah politik.
- Maraknya money politic dalam berbagai proses politik.
- Meluasnya kriminalitas dan terorisme serta konflik-konflik horizontal.
- Berkembangnya etno-centrisme, fanatisme dan radikalisme.
- Kebutuhan pangan bagi rakyat yang semakin tergantung dari import dengan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi.
Masalah-masalah yang dihadapi negara kita itu bukanlah yang pertama kali terjadi di dunia ini. Masalah-masalah yang terjadi di negara kita itu telah pernah dialami oleh banyak negara lain dan banyak yang dapat mengatasinya dengan sukses.
Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara tersebut untuk mengatasi berbagai masalah tadi, dan sebagai bangsa dengan budaya paternalistik, masalahnya bisa menjadi lebih sederhana jika hadir pemimpin yang dapat memberi suri ketauladanan.
Saat di setiap pemukiman perlu tersedia, dalam jumlah yang cukup, dengan mutu yang layak, aman dikonsumsi dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
Sejak beberapa tahun terakhir ini, muncul kerisauan atas menurunnya kemampuan kita untuk memenuhi sendiri kebutuhan pangan bagi rakyat Indonesia. Dunia pun diliputi kekhawatiran itu, karena penduduk bertambah menurut deret ukur sedangkan produksi pangan bertambah menurut deret hitung. Menurut FAO, pada waktu ini di dunia terdapat ± 200 juta orang kekurangan pangan.
Penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi 2 kali lipat dan jumlahnya sekarang, menjadi ± 400 juta jiwa. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terjadi pula peningkatan konsumsi/kapita untuk berbagai pangan. Akibatnya, dalam waktu 35 tahun yang akan datang Indonesia memerlukan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali jumlah kebutuhan saat ini.
Penduduk Indonesia 1900 - 2035
Tahun
Jumlah
1900
1930
1960
1990
2000
2035
40 juta
60 juta
95 juta
180 juta
210 juta
400 juta
Diawal abad ke 20, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah 20 juta jiwa, dan diawal abad 21, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah hampir 200 juta jiwa. Penduduk Indonesia menjadi 5 kali lipat dalam waktu 100 tahun.
Pada waktu ini, rata-rata konsumsi pangan per kapita per tahun rakyat Indonesia untuk beberapa pangan penting adalah sebagai berikut:
1.Beras 133 kg (tertinggi di dunia)
2.Jagung 5,93 kg
3.Ikan 12,5 kg (rata-rata dunia 16 kg)
4.Ayam 3,8 kg (Malaysia 23 kg, Filipina 4 kg, Thailand 16,8 kg, Vietnam 1 kg) Indonesia berpotensi bertambah 2 kg dalam waktu 5 tahun yang akan datang, yang berarti tambahan kebutuhan 400 juta kg/tahun.
5.Daging 7,10 kg
6.Telur 52 butir (Malaysia 300 butir, Filipina 70 butir, Thailand 100 butir, Vietnam 40 butir) Indonesia berpotensi bertambah 10 butir dalam waktu 5 tahun yang akan datang, yang berarti tambahan kebutuhan 2 milyard butir/tahun
7.Susu 6,50 kg
8.Ketela pohon 9,93 kg
9.Buah-buahan 40,06 Kg (Jepang 120 kg, rekomendasi FAO 65,75 kg, Amerika 75 kg)
10.Gula 15,6 kg (rata-rata dunia 25,1 kg)
11.Kedelai 6,01 kg (rata-rata dunia 7 kg)
12.Sayur-sayuran 37,94 kg (rekomendasi FAO 65,75 kg, Amerika 95 kg)
Konsumsi Daging, Telur dan Susu beberapa Negara
No.
Negara
Konsumsi (Kg/Kap/Thn)
Daging
Telur
Susu
1
2
3
4
5
6
7
Indonesia
Bangladesh
China
Japan
Malaysia
Philippines
Thailand
7,10
3,08
39,00
25,97
46,87
24,96
25
3,48
0,68
10,1
20,54
17,62
4,51
9,15
6,50
31,55
2,96
10,72
3,82
0,25
2,04
(Sumber: HKTI, diolah dari berbagai sumber)
Kecuali beras, untuk pangan yang lain konsumsi/kapita/tahun rakyat Indonesia masih rendah, dan berpotensi meningkat dengan meningkatnya pendidikan, pengetahuan akan gizi dan kesejahteraan rakyat, yang akan menuntut peningkatan penyediaan pangan yang amat besar. Kedepan, akan terjadi lonjakan kebutuhan pangan yang amat besar. Pasar pangan amat besar yang kita miliki perlu kita gunakan untuk memperkuat pertanian kita, Jika salah penanganan, pasar pangan amat besar yang kita miliki itu, akan dimanfaatkan dengan baik sebagai pasar yang empuk oleh produser pangan dan luar.
Inilah hal pertama yang ingin saya sampaikan. Membahas masalah pangan bagi negara dengan penduduk yang demikian besar seperti negara kita, berarti membahas masalah sangat penting dari masa depan negara kita. Pada waktu ini, untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk yang jumlahnya ± 200 juta jiwa, setiap tahunnya Indonesia sebaqai negara agraris, harus mengimpor, jagung lebih dari 1 juta ton, kacang tanah ± 0,8 juta ton, kacang hijau ± 0,3 juta ton, dan gaplek ± 0,9 juta ton.
Import beras di tahun 1998, sebesar 5,8 juta ton, dan 4 juta ton pada tahun 1999 serta rata-rata 2 juta ton/tahun, telah menjadikan Indonesia importir beras terbesar di dunia, padahal 14 tahun sebelumnya, kita telah mampu berswasembada beras. Impor biji kedelai pada lima tahun terakhir rata-rata 0,8 juta ton pertahun senilai US$ 226,838 juta setara Rp. 2,3 Triliun (1 US$ = Rp. 10.000,-) padahal hanya 15 tahun sebelumnya kita mampu berswasembada. Produksi kedelai dalam negeri terus menurun 0,81%/tahun, sementara kebutuhan terus meningkat 2,41%/tahun, dari 2.312.000 ton di tahun 1998, menjadi 2.737.000 ton di tahun 2005. Dengan import kedelai 1.156.058 ton di tahun 1999, senilai US$ 254 juta, menjadikan Indonesia importir kedele untuk pangan manusia terbesar di dunia. Luas areal tanaman kedelai tahun 1992 adalah 1,67 juta Ha, turun tinggal 0,8 juta Ha (separuhnya) di tahun 2000, karena membanjirnya kedelai import yang murah. Di tahun 2000 import kedelai meningkat menjadi Rp 4,7 Triliun.
Pada waktu ini, bea masuk kedelai 0%, dengan harga ± Rp. 1.500,- - Rp. 1.600,-/kg, sangat memukul petani karena biaya produksi kedelai dalam negeri Rp. 2.100,- - Rp. 2.200,-/kg. Sebaiknya, Pemerintah mengenakan bea masuk kedelai 50% agar terbentuk harga di pasar sekitar Rp. 2.500,-/kg. Harga komoditas pertanian yang rendah, disincentive bagi peningkatan produksi.
Produksi gabah/beras pada tahun 2001 = 50,18 juta ton GKG setana dengan 29,8 juta ton beras, turun sekitar 3,31 pensen dari produksi tahun sebelumnya (51,89 juta ton GKG). Selain gabah/beras dan kedelai, komoditas pangan lainnya (jagung, kacang tanah, ubi jalar, dan ubi kayu) dalam tahun 2001 mengalami penurunan. Hanya kacang hijau yang produksinya mengalami peningkatan dibanding tahun 2000.
Produksi Padi dan Palawija Tahun 2000 dan Perkiraan Tahun 2001 (Juta Ton)
Komoditas
2000
2001
Perubahan (%)
Padi (GKG)
51,89
50,18
-3,31
Jagung
9,67
9,29
-3,92
Kedelai
0,73
0,92
-9,27
Kacang tanah
1,01
0,70
-3,66
Kacang hijau
0,28
0,34
20,41
Ubi jalar
1,82
1,61
-11,90
Ubi kayu
16,08
15,60
-3,01
Sumber : BPS, Angka Ramalan II Tahun 2001
Penyebab utama penurunan produksi adalah karena tidak adanya rangsangan untuk meningkatkan produksi, karena rendahnya harga. Selama 6 kali panen sejak tahun 1998, harga beras juga kedelai terus tertekan amat rendah. Perlu pula kita cermati bahwa masyarakat kita akhir-akhir ini, dengan kecepatan yang meningkat semakin banyak mengkonsumsi roti dan mie, yang bahan bakunya gandum, bahan makanan yang belum dapat kita produksi sendiri. Jenis-jenis makanan Eropa/Amerika berupa roti, hamburger, serta makanan Jepang, kuat sekali merasuk ke masyarakat kita khususnya golongan berpenghasilan tinggi. Akibatnya, sejak tahun 1996 setiap tahun kita mengimport gandum 4,5 juta ton.
Selama 5 tahun terakhir, rata-rata setiap tahun kita mengimport gula 1,6 juta ton, menjadikan Indonesia importir gula no. 2 terbesar di dunia setelah Rusia, padahal semasa penjajahan Belanda kita adalah exportir gula terbesar No. 2 di dunia. Sekarang kita import sapi ± 400.000 ekor/tahun, merupakan negara tujuan export sapi Australia yang terbesar, padahal di tahun 70-an, kita masih menjadi exportir sapi. Di Western Australia sekarang ini sedang dipersiapkan peternakan kambing secara besar-besaran yang studinya menyebutkan untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia.
Pada waktu ini, Indonesia merupakan negara pengimpor pangan yang amat besar. Di tahun 2000, impor Indonesia atas delapan komoditas pangan yaitu gandum, jagung, beras, biji dan bungkil kedelai, kacang tanah, gula pasir dan bawang putih, mencapai nilai Rp 16,62 triliun.
Volume dan Nilai Impor Delapan Komoditas Pangan Tahun 2000
No
Komoditas
Volume
(ton)
Nilai
(dolar AS)
1
Gandum
3.576.665
500.312.470
2
Jagung
1.236.764
150.012.707
3
Beras
550.514
131.132.613
4
Biji kedelai
1.277.685
275.481.226
5
Bungkil kedelai
1.262.040
268.746.270
6
Kacang tanah
111.284
35.601.776
7
Gula pasir
1.680.275
290.873.225
8
Bawang Putih
174.702
44.120.000
J u m l a h
9.869.929
1.696.280.287
Dengan kurs Rp 9,800,- per dolar AS, nilai komoditas itu setara dengan Rp 16,62 triliun.
Sumber: HKTI, diolah dari berbagai sumber
Disamping itu, menurut BPS, impor Indonesia tahun 2000 atas buah segar seperti: apel volume impornya 73.426 ton dengan nilai 42,42 juta dolar AS, jeruk 19.438 ton dengan nilai 10,8 juta dolar AS, jeruk mandarin 58.423 ton dengan nilai 30,04 juta dolar AS. Impor Indonesia atas sayuran seperti: bawang 13.358 ton dengan nilai 3,4 juta dolar AS, dan kentang 4.569 ton dengan nilai 1,4 juta dolar AS. Import pangan dirangsang oleh pertama, kebutuhan dalam negeri yang amat besar; kedua, harga di pasar international yang rendah, ketiga, produksi dalam negeri yang tidak mencukupi; dan keempat, adanya bantuan kredit impor dari negara eksportir.
Harga di pasar International yang rendah, terbentuk oleh hadirnya residual goods (bahan-bahan yang harganya sangat murah karena di negara produsernya tidak laku dijual, seperti paha ayam dari Amerika Serikat dan jerohan ternak dari Australia serta kelebihan produksi yang melimpah dari negara-negara produsen yang dilempar keluar negerinya, agar harga di dalam negerinya tetap tinggi, seperti gula dari Australia yang di pasar dalam negeri Australia harganya Rp. 5.000,-/kg; kelebihan produksinya di lempar ke Indonesia dengan harga Rp. 2.100,-/kg; juga gula India, beras Thailand, beras Vietnam, tembakau Cina, jeruk Cina dari Taiwan dan lain-lain) yang telah ikut rnenghancurkan pertanian Indonesia.
Pada tahun ini, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA - United State Departement of Agriculture) memberikan bantuan kredit melalui GSM-108, senilai 650 juta dollar AS dengan bunga yang sangat rendah kepada para importir Indonesia untuk mengimport produk pertanian Amerika Serikat terutama kedelai, jagung, gandum dan beras. Pengembalian kredit ini sangat ringan dan dalam jangka panjang. Para importir sangat menikmati fasilitas ini, karena sebelum kredit dikembalikan, para importir dapat memanfaatkannya terlebih dahulu. Kondisi ini juga membuat banyak pihak tidak ingin melihat kita membangun kemandirian di bidang pangan, dan telah ikut menjadi penyebab merosotnya produk-produk pertanian kita.
Negara-negara maju dalam membantu negara-negara berkembang, juga mementingkan kepentingan nasionalnya. Amerika memberi kredit pangan, membantu petaninya agar semakin kuat, Presiden George Bush baru saja mengesahkan Act baru yang memberi plafond subsidi untuk pertanian Amenika sebesar 82 milyard US$ dalam 10 tahun. Jepang membantu pembangunan jalan. Agar mobil-mobil Jepang lebih banyak terjual.
Tanpa perencanaan yang matang dan langkah-langkah strategis yang konsisten untuk meningkatkan produksi pangan, Indonesia sebagal negara agraris dalam anti mayoritas angkatan kerjanya bekerja di bidang pertanian, akan terus menjadi negara “nett importir” pangan yang sangat besar, yang akan terus semakin membesar, yang pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional kita.
Inilah hal kedua yang ingin saya nyatakan, yaitu bahwa negara-negara maju dalam membantu negara-negara berkembang, mengutamakan memperkuat basis perekonomiannya sendiri; antara lain memperkuat petaninya.
Kita memang hidup di dunia yang oleh banyak orang disebut “The Borderless World”, dunia yang tanpa batas, dengan arus barang, orang, modal dan uang serta teknologi dan budaya yang hampir-hampir tanpa hambatan, sehingga masalah import pangan bukanlah sesuatu yang harus ditabukan. Tetapi karena penduduk kita banyak dan potensinya ada, sebaiknyalah kita mampu memenuhi sendiri kebutuhan pangan kita. Kita harus semakin cerdik hidup di “ The Borderless World” ini.
Sampai dengan tahun 1970-an, banyak tulisan dari pakar memperkirakan bahwa masa depan pangan dunia akan dapat dipenuhi dari negara-negara dunia ketiga, di antaranya Brazilia, Argentina, India, China juga Australia dan Indonesia karena wilayahnya yang luas, sementara negara-negara maju akan lebih mengkonsentnasikan diri pada industri maju berteknologi tinggi, yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Tetapi sejak akhir tahun 1980-an, dengan ditemukannya teknologi kloning untuk ternak, bioteknologi rekayasa genetika (Organisme Hasil Modifikasi-OHM), dunia kembali berharap bahwa kebutuhan pangan masa depan dunia akan datang dari negara-negara maju.
Jika harga pangan di pasar dunia semakin murah (yang disebabkan oleh banjirnya residual goods, barang-barang kelebihan dari negara-negara produser yang dilempar ke pasar internasional seraya menjaga harga di dalam negerinya yang tinggi), negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia akan semakin tergantung pada pangan impor dan upaya membangun kemandirian pangan semakin sulit. Instrument yang tersedia dan diperbolehkan oleh aturan-aturan WTO untuk menghambat impor adalah tariff bea masuk. Sebagai contoh biaya produksi 1 Kg ayam hidup di Indonesia adalah ± Rp 6.500,- dan ini termurah di Asean. Ayam potong menjadi ± Rp 9.500,-/Kg sementara paha ayam Amerika di negerinya tidak dimakan orang, dijual di Jakarta Rp 4.500,-/Kg. Biaya produksi gula di Indonesia ± Rp 2.300,-/Kg. Sementara gula import ex Australia masuk Tanjung Priok dengan harag Rp 1.700,-/Kg, tetapi harga di pasar-pasar Canbera ± Rp 4.500,-Kg. Beras Thailand seharga US $ 160/ton atau ± Rp 1.550,-/Kg. Berhadapan dengan biaya produksi di Indonesia ± Rp 2.300,-/Kg, tetapi harga beras di Bangkok ± Rp 3.800,-/Kg. Thailand setiap tahun surplus beras ± 2 juta ton. Ini disebut residual trading.
Perlu disadari oleh semua pihak, petani, masyarakat luas, pemerintah dan Lembaga Legislatif bahwa :
- Kemampuan kita disbanding pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, relatif telah dan sedang menurun dengan sangat besar.
- Pada waktu ini Indonesia berada dalam keadaan “Rawan Pangan” bukan karena tidak adanya pangan, tetapi karena pangan untuk rakyat Indonesia sudah tergantung dari supply luar negeri, dan ketergantungannya semakin besar.
- Pasar pangan amat besar yang kita miliki diincar oleh produsen pangan luar negeri yang tidak menginginkan Indonesia memiliki kemandirian di bidang pangan
Inilah kesimpulan yang ingin saya nyatakan mengenai kondisi pangan kita pada waktu ini. Bagian berikut menyangkut masa depan pangan kita.
Pada tahun 2035, dengan jumlah penduduk sebanyak ± 400 juta jiwa, kebutuhan beberapa jenis pangan untuk Indonesia setiap tahunnya diperkirakan :
No
Jenis
Konsumsi/Kapita/th
Tahun 2035
Kebutuhan Nasional Tahun 2035
Produksi dalam Negeri Tahun 2001
Keterangan
1
Beras
90 Kg (turun 30%)
36 juta ton
29 juta ton
+ 25%
2
Daging (ayam,sapi,dll)
15 Kg (naik 2 X)
6 juta ton
2,2 juta ton
3 Kali
3
Telur
90 Butir (naik 3 X, masih di bawah Malaysia
36 M butir
12,6 M butir
3 Kali
4
Susu
12 liter
4,8 M liter
1,2 M butir
4 Kali
5
Gula
25 Kg
10 juta ton
1,9 juta ton
5 Kali
6
Ayam
8 Kg
3,2 juta ton
750 ribu ton
4 Kali
Tampak bahwa kebutuhan beberapa jenis pangan untuk rakyat Indonesia di tahun 2035, sangat besar bila dibandingkan dengan kemampuan produksi kita pada waktu ini. Diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang memadai untuk memenuhi tuntutan produksi yang begitu besar itu, bila kita ingin mandiri di bidang pangan.
Pertanyaan awalnya adalah, apakah kita ingin dapat memenuhi sendiri kebutuhan pangan yang begitu besar itu. Kalau ingin apakah mampu dan caranya bagaimana ?
Mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia, dan karena tersedia lahan yang cukup luas dan tenaga kerja pertanian yang cukup banyak, serta begitu besarnya devisa yang terkuras untuk impor pangan, dan mengingat sangat terbatasnya devisa yang kita miliki, dan kebutuhan negara yang sangat besar untuk membayar bunga dan cicilan hutang (luar negeri) hampir 150M $ terbesar No. 4 di dunia, Indonesia perlu berusaha semaksimal mungkin MENCUKUPI KEBUTUHAN PANGANNYA SECARA MANDIRI, dalam waktu yang tidak terlalu tama (± 10 tahun). Hal ini sepatutnya menjadi keputusan politik negara. Diperlukan upaya khusus untuk sampai pada keputusan potitik ini.
Mandiri dalam bidang pangan dalam arti kita mampu memproduksi sendiri produk-produk pertanian/pangan yang kita butuhkan dengan dukungan unsur-unsur pendukungnya (benih, alsintan, pupuk, obat-obatan dan lain-lain) yang dapat kita sediakan sendiri. Selanjutnya menjadi negara exportir pangan. Kemandirian di bidang pangan lebih dari sekedar swasembada yang dapat didukung oleh alsintan, pupuk dan obat-obatan import seperti yang telah pernah kita capai di tahun 1984, tetapi dengan dukungan traktor, pupuk, benih, obat-obatan made in Indonesia.
Bukan hanya di bidang pangan, secara umum bangsa yang berpenduduk sangat banyak, 210 juta jiwa, no 4 terbanyak di dunia ini, harus segera dapat membangun kemandirian ekonominya, agar Indonesia mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi bangsa ini. Tap MPR RI No II/MPR/2002 dan Tap MPR RI No. VI/MPR/2002 telah juga mengamanatkan hal tersebut. UUD 1945 perubahan ke ernpat juga telah menetapkan kemandirian sebagai salah satu prinsip pembangunan ekonomi Indonesia. Proklamator kemerdekaan Indonesia Bung Karno, dalam semangat kemandirian itu menganjurkan kita melaksanakan Tri Sakti yaitu : berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Sementara itu, meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat membuat masyarakat menuntut kwalitas pangan yang lebih bergizi, lebih enak, lebih higienis dan lebih aman. Dunia juga menuntut pangan yang lebih berkwalitas.
Pada waktu ini, banyak export pangan kita yang ditolak FDA dari USA, dan menjadikan harga export produk-produk pertanian dan pangan kita harganya tertekan. Pada waktu yang akan datang, peningkatan kwalitas produk pertanian dan pangan perlu memperoleh perhatian yang memadai. Begitu besar tantangan yang dihadapi di bidang produksi pangan, yaitu peningkatan volume produksi, peningkatan kwalitas produk dan penganekaragaman produk serta meningkatkan daya saingnya.
Secara umum di bidang pertanian, juga peternakan dan perikanan diperlukan perubahan-perubahan yang mendasar, terutama dengan meningkatkan skala usaha petani, perikanan dan peternakan kita, menjadikan setiap usaha tani, usaha peternakan dan usaha perikanan mencapai skala ekonomi yang dapat membuat pelakunya sejahtera.
Hal ini adalah suatu keharusan, kalau kita ingin membuat petani, peternak dan nelayan kita sejahtera, membuat produksinya berdaya saing tinggi, serta ingin membangun kemandirian di bidang-bidang itu. Perluasan lahan usaha per KK petani merupakan persyaratan utama.
Ada beberapa permasalahan mendasar yang perlu memperoleh penanganan serius dalam upaya kila membangun kemandirian di bidang pangan:
Pertama, semakin mengecilnya rata-rata penguasaan lahan pertanian per KK petani, dari 0,93 hektar pada tahun 1983, menjadi 0,83 hektar pada tahun 1993. Di luar Pulau Jawa menurun dari 1,38 hektar menjadi 1,19 hektar, dan di Pulau Jawa menurun dari 0,58 hektar menjadi 0,47 hektar, sekarang diperkirakan 0,3 Ha. Sebagian besar (43 persen RTP) merupakan kelompok tunakisma atau petani yang memiliki lahan pertanian kurang dari 0,1 ha.
Struktur Penguasaan Tanah Pertanian di Indonesia (1993)
No
Kelompok Luasan
Penguasaan (Ha)
Rumah Tangga Petani
%
%
Kumulatif
% LuasTanah
Yang Dikuasai
1
Tunakisma dan
petani kurang 0,1
43
43
13
2
0,1 - 0,49
27
70
18
3
0,5 - 0,99
14
84
4
>1,0
16
100
69
Sumber : Sensus Pertanian Indonesia, Tahun 1993
Semakin mengecilnya rata-rata penguasaan lahan pertanian oleh RTP tersebut disebabkan oleh terjadinya fragmentasi pemilikan, bertambahnya jumlah petani dan karena alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Berdasarkan data dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah terjadi alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian di Pulau Jawa untuk permukiman dan industri antara tahun 1994 - 1999, seluas 81.176 hektar terdiri dari permukiman seluas 33.429 hektar dan industri seluas 47.747 hektar. Alih fungsi tanah pertanian tersebut yang terluas di Jawa Barat (79,41 persen), Jawa Timur (17,01 persen), Jawa Tengah (2,69 persen), cukup kecil dan Daerah Istimewa Yogyakanta (0,89 persen).
Teman saya seorang petani Belanda menyatakan bahwa sebelum PD II, rata-rata petani Belanda menggarap lahan seluas 14 Ha. Pada waktu ini, dengan berkurangnya jumlah petani (adanya perluasan areal pertanian di polder-polder baru, rata-rata petani Belanda menggarap 75 Ha, dengan mekanisasi yang semakin canggih, menjadikan Negeri Belanda yang tanahnya sempit itu, exportir hasil pertanian yang terbesar di Eropa. Di Negeri Belanda, lahan pertanian tidak boleh dibagi untuk diwariskan. Dia juga menyatakan bahwa daya saing sangat tinggi yang dimiliki petani Belanda terjadi karena lahan usaha petani yang terus semakin luas, yang telah mendorong meningkatkan mekanisasi yang semakin maju.
Kedua, semakin bertambahnya jumlah rumah tangga petani (RTP) yang menguasai lahan di bawah 0,5 hektar. Pada tahun 1983, jumlah petani gurem 9,53 juta RTP, dan sepuluh tahun kemudia’ (1993) meningkat menjadi 10,94 juta RTP, di mana 74 persen di antaranya berada di PuIa Jawa. Angka statistik tersebut menunjukkan, bahwa dalam jangka waktu sepuluh tahun terdapat penambahan 1,41 juta RTP gurem.
Kedua hal ini, yaitu menyempitnya lahan pengusahaan petani dan meningkatnya jumlah petani gurem, merupakan hambatan besar bagi upaya peningkatan produktivitas dan kwalitas hasil pentanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Membiarkan proses fragmentasi lahan berlangsung terus, akan membuahkan petani dan peternak yang semakin miskin, juga akan membuat produk-produk pertanian dan peternakan kita tidak memiliki daya saing yang tinggi baik dari segi kwalitas maupun harga. Dengan membiarkan hal itu, kita tidak akan pernah mampu memenuhi sendiri kebutuhan pangan kita.
Inilah hal pertama yang ingin saya nyatakan tentang masa depan pangan kita.
Ketiga, rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) apabila dibandingkan dengan Nilai Tukar Industri atau lainnya. Hal itu semakin mempersulit kehidupan petani dan menurunkan motivasi petani dalam berusaha tani. Kebijakan harga pangan murah yang telah berlangsung lama, sangat merugikan petani. Dengan harga pangan yang murah, upah buruh menjadi murah dan inilah salah satu daya tarik investasi. Terkesan terjadi subsidi terselubung dari sektor pertanian kepada sektor industri.
Pemerintah Pusat dan Daerah perlu membantu upaya perluasan lahan pengusahaan per KK petani lengan memberi kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan-lahan negara. Pemerintah Pusat dan Daerah yang wilayahnya luas perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk perluasan areal pertanian di lahan kering. Perluasan areal pertanian di lahan kering relatif lebih murah, sekitar Rp 4 Juta/ha, dibanding dengan investasi lahan sawah beririgasi yang ± Rp 12 juta/Ha. Di era otonomi daerah ini kemampuan daerah-daerah untuk mewujudkan perluasan areal pertanian dan perluasan lahan pengusahaan petani tidaklah sama. Propinsi-Propinsi yang luas dan kaya seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Jambi, Sumatera Selatan dapat segera mengembangkan pertanian dan peternakan yang luas milik petani dengan mekanisasi. Jumlah petani juga perlu berkurang dengan alih profesi yang direncarakan dan dipersiapkan.
Ketahanan pangan yang terlalu bergantung pada satu komoditi beras, mengandung resiko bahwa kebutuhan pangan rumah tangga dan nasional akan rapuh. Oleh karenanya, ke depan kita perlu meningkatkan upaya pengembangan pangan alternatif yang berbasis umbi-umbian (ubi, ketela, garut, dll), tanaman pohon (sukun dan sagu), serta bahan pangan berbasis biji-bijian (beras, jagung, sorgum, dli), yang dapat diproses menjadi tepung yang bisa diolah menjadi aneka produk makanan yang mempunyai nilai tambah tinggi. Di Thailand, makanan berbasis tepung singkong variasinya banyak sekali.
Masyarakat kita perlu mengembangkan makanan berbasis tepung, yang bisa tahan lebih lama, dapat diperkaya dengan mineral dan vitamin, serta lebih fleksibel pengolahannya. Mengembangkan bahan pangan tepung tidak harus berupa industri besar, sebab jagung atau beras dapat ditumbuk atau digiling dengan mesin giling tepung yang tersebar di desa-desa penghasilnya, sementara untuk membuat tepung sagu, teknologinya telah dikuasai masyarakat lokal. Sayangnya teknologi pemanfaatan tepung dan bahan yang dapat kita produksi sendiri seperti tepung tapioka, tepung beras, tepung jagung, tepung sagu belum berkembang dengan baik untuk menjadi bahan baku roti, pengganti gandum. Penggunaan yang umum baru pada produk kueh/makanan ringan.
Sekalipun potensi bahan pangan alternatif yang kita miliki cukup besar dan beragam, tetapi dalam pengembangannya bukanlah perkara mudah. Kita dihadapkan pada berbagai kendala yang cukup mendasar. Di samping kendala teknis dan pembiayaan, ada juga kendala budaya sosial dan psikoiogis berupa pandangan bahwa beras merupakan makanan bergengsi (superior food) sedang umbi-umbian, sagu, sukun, jagung, dll merupakan makanan inferior (inferior food), sementara gandum bukan makanan yang dapat kita produksi sendit.
Masyarakat luas bersama Pemerintah perlu pula terus menerus melaksanakan sosialisasi dan kampanye diversifikasi pangan, disertai bimbingan teknis dan insentive ekonomi dari pangan pokok beras kepada pangan pokok lokal lainnya, atau dengan campuran untuk mengurangi konsumsi beras antara lain dengan beras jagung, sagu, jagung, ubi dan lain-lain. Penggantian 10% kebutuhan pangan yang semula beras ( setara ± 3,1 juta ton/tahun) dengan pangan selain beras, akan membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor beras.
FAO (Food and Agriculture Organization) melalui siaran persnya nomor 00/43, menyebutkan antara lain:
Dalam waktu 30 tahun yang akan datang, peningkatan produksi pangan akan lebih besar daripada pertambahan penduduk. Peningkatan produksi yang tinggi itu terjadi di negara maju. Kecukupan pangan dan kwalitas makanan akan membaik, tetapi jumlah penduduk dunia yang kekurangan pangan meningkat.
Produksi hasil-hasil pertanian dunia meningkat semakin melandai, dari 2,1%/tahun selama 20 tahun terakhir, menjadi 1,6%/tahun antara tahun 2000 - 2015 dan menjadi 1,3%/tahun antara tahun 2015 - 2030, sementara pertambahan penduduk dunia antara tahun 2000 - 2015 sebesar 1,2%/tahun dan 0,8% diantara tahun 2015 - 2030. Dengan jumlah penduduk mencapai 8 miliar di tahun 2030, kekurangan pangan tetap akan mengancam dunia. Di tahun 2015 diperkirakan 580 juta penduduk dunia akan mengalami kekurangan pangan. Makanan pokok penduduk tetap berasal dari biji-bijian, yang memasok setengah dari kalori makanan. Kebutuhan biji-bijian akan berkisar 50 persen untuk konsumsi manusia, 44 persen makanan ternak dan 6 persen industri. Negara-negara berkembang akan semakin tergantung pada bahan pangan impor.
Impor biji-bijian negara-negara berkembang akan meningkat hampir 2 kali lebih besar dalam waktu 35 tahun yang akan datang, dari 170 juta ton di tahun 1995 menjadi 270 juta ton di tahun 2030. Negara-negara yang secara tradisional merupakan exportir biji-bijian, seperti Amerika Utara, Eropa Barat, dan Australia perlu meningkatkan ekspor bahan pangannya dari 142 juta ton di tahun 1995 menjadi 280 juta ton di tahun 2030.
Bagi saya pribadi, sangatlah meresahkan membaca siaran pers FAO tersebut, di mana FAO justru mendorong sekaligus merekomendasikan negara-negara seperti Amerika Utara, Eropa Barat, dan Australia meningkatkan ekspor bahan pangannya. Mengapa FAO tidak menganjurkan membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia meningkatkan produksi pangannya. Sepatutnyalah kita menyadari bahwa negara-negara maju produsen pangan yang melimpah itu, tidak akan merelakan Indonesia memiliki kemandirian di bidang pangan.
Indonesia dengan jumlah penduduknya yang banyak, merupakan pasar pangan yang amat besar yang diincar oleh negara-negara produsen pangan. FAO dan banyak lembaga-lembaga International lain dalam membantu negara negara berkembang, sangat diwarnai oleh kepentingan negara-negara maju, sesuatu yang wajar dalam peradaban manusia yang semakin menjadi Homo Economicus.
Dengan kindisi daya saing pertanian Indonesia saat ini liberalisasi perdagangan ASEAN yang akan diwujudkan dalam Asean Free Trade Area (AFTA) tahun 2003 yang akan datang, harus dicermati sebagai bahaya besar bagi hidup matinya pertanian Indonesia. Di bidang pertanian untuk produk-produk tertentu Indonesia belum siap memasuki AFTA 2003, tanpa langkah-langkah yang tepat, belum siap menghadapi Pasar Bebas Asia Pacific 2010 dan Pasar Bebas Dunia 2020. Jika kita tidak mampu mengelola dengan baik pensaingan yang akan terjadi, maka kehancuran pertanian Indonesia akan menjadi kenyataan, yang berarti jutaan petani Indonesia akan kehilangan pekerjaan dan akibatnya pangan bagi rakyat Indonesia akan semakin tengantung dari import.
Tuntutan peradaban masyarakat dunia membawa kita pada kehidupan yang semakin liberal, semakin demokratis, dan manusia semakin menjadi homo economicus, yang menempatkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi sebagai pertimbangan utama dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karenanya, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda utama semua pemerintahan di muka bumi ini. Dan karena mayoritas rakyat Indonesia adalah petani, maka peningkatan kesejahteraan petani perlu memperoleh perhatian dari semua pihak, terutama Pemerintah. Peningkatan kesejahteraan yang terjadi atas dasar peningkatan produktivitasnya. Masyarakat menuntut kehidupan yang semakin nyaman, kwalitas hidup yang semakin baik, pelayanan yang semakin cepat; makanan yang semakin lezat, gizi yang semakin baik, keamanan pangan yang semakin tinggi, dan oleh karenanya bagi semua pelaku kegiatan ekonomi dituntut untuk menghasilkan roduk yang semakin banyak dan semakin baik, dengan pelayanan yang semakin cepat dan nyaman serta persaingan harga yang semakin ketat. Persaingan hidup antar bangsa, antar anggota masyarakat dan antar individu yang semakin tinggi tidak dapat dielakkan.
Dalam suasana yang seperti itu, yang harus kita lakukan sebagai suatu bangsa adalah terus-menerus melakukan peningkatan produktivitas dan kwalitas produk-produk kita, membangun daya saing yang semakin tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah hal ketiga yang ingin saya nyatakan tentang masa depan pangan kita. Gagasan pemerataan yang tidak didasari oleh semangat itu akan bertentangan dengan kecenderungan peradaban manusia, bertentangan dengan tuntutan kemajuan, yang akhirnya akan menyulitkan kita sendiri, menjerumuskan kita ke dalam lembah kemiskinan struktural yang sangat sulit untuk mengatasinya. Tersedia cara-cara untuk melakukri pemerataan sekaligus meningkatkan kwalitas dan produktivitas; walaupun hal itu tidaklah mudah.
Pengalaman masa lalu kita menunjukan bahwa sebagai suatu bangsa kita telah membiarkan berlangsungnya proses menyempitnya lahan pengusahaan petani kita, yang telah mengakibatkan para petani pnoduktivitasnya rendah dan menjadi miskin, sementara petani-petani di negara lain lahannya terus semakin meluas. Walaupun kita memiliki pakar yang cukup banyak di bidang gula dan memiliki pengalaman yang panjang sebagai produsen utama, kita telah membiarkan proses menurunnya tingkat produktivitas gula yang berlangsung bertahun-tahun secara bertahap. Di zaman Belanda, tingkat produktivitas gula kita 15 ton/Ha, dan sekarang tinggal 4,5 ton/Ha.
Penurunan tingkat produktivitas gula di Pulau Jawa tidak tenjadi secara mendadak, tetapi bertahap merosot terus, dan kita sekalian, Pemerintah, pabrik gula dan petani, seperti tak mampu mengerem kemerosotan itu. Zaman Belanda produksi gula 15 ton gula/ha, di akhir tahun 50 an =10 ton gula/ha, akhir tahun 60 an = 8 on gula/ha.
Selanjutnya di tahun 1975 diterbitkan Inpres IX/75, yang semakin memerosotkan produktivitas gula di P. Jawa, dan sekarang tinggal 4,5 ton gula/ha
Di waktu yang lalu, sewaktu ditemukan teknologi baru penangkapan ikan dengan trawl, kita bukannya membina nelayan untuk lebih produktf dengan menggunakan trawl, tetapi malah melarangnya dengan alasan pelestarian lingkungan. Sekarang trawl ini digunakan secara luas di Thailand, Jepang dan banyak negara lain di dunia, dan rnenjadikan nelayan kita tidak produktif mengais-ngais ikan di tepi pantai dengan peralatan yang kuno. Export ikan Thailand yang luas lautnya tidak lebih luas dari laut Jawa Tengah itu, lebih besar dari export Indonesia yang luas lautnya 5 juta Km2. Di Australia, tidak ada peternak s yang jumlah sapinya kurang dari 200 ekor.
Di Jepang orang tidak akan bertani kalau lahannya kurang dari 1 Ha. Dan lahan seluas itu digarap sangat intensif; banyak yang seluruhnya di dalam Green House. Di Belanda, lahan pertanian dilarang dibagi untuk diwariskan. Sebagai suatu egara, jangan ada kebijakan yang mendorong menurunkan prestasi produktivitas dan kwalitas. Juga di pendidikan seperti meluluskan semua peserta ujian SLTA, membiarkan tanpa hukuman siswa yang berantem dan lain-lain. Semua bangsa di negana-negara yang maju berlomba-lomba mensejahterakan warganya dengan bantuan negara, memenuhi tuntutan kemajuan peradaban manusia dengan cara-cara yang memenuhi kaidah-kaidah ekonomi, memperkuat basis ekonomi ekonomi warganya. Sangat besar subsidi negara untuk petani di Eropa. Dengan alasan yang sama, keluar pula kredit export oleh US DA untuk membantu petani Amerika. Walaupun luas laut kita 5 juta km2, dengan panjang pantai 88.000 km, no. 2 di dunia setelah Canada, dan air laut kita tetap asin, setiap tahun Indonesia mengimport garam lebih dari 1 juta ton, karena petani-petani garam tidak didorong untuk menggunakan teknologi modem, yang lebih produktif.
Agar penbangunan pertanian memiliki arah yang jelas, negara perlu menetapkan politik pertanian yaitu keputusan sangat mendasar dibidang pertanian pada tingkat negara, yang menjadi arah ke depan, untuk menjadi acuan semua pihak yang terlibat, dengan sasaran membangun kemandirian di bidang pangan. Menurut hemat saya, kalau kita ingin sukses dalam persaingan di bidang pertanian di “The Borderless World” ini, beberapa sasaran perlu ditetapkan untuk di upayakan oleh semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, petani dan masyarakat luas.
Beberapa sasaran yang penting itu adalah :
1. Perluasan areal pertanian, khususnya di lahan kering yang besarnya perlu diteliti, paling tidak 200.000 Ha/tahun, dimana 40.000 Ha untuk menggantikan areal pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian.
2. Peningkatan skala usaha petani, peternak dan nelayan; untuk petani, perluasan areal pengusahaan petani dari rata-rata 0,3 Ha/KK di tahun 2001, menjadi rata-rata 8 Ha di tahun 2030 dan mengembangkan mekanisasi.
3. Pengurangan jumlah petani baik prosentasenya terhadap angkatan kerja maupun nominalnya dari ± 48% di tahun 2001 (22,5 juta) menjadi ± 15% di tahun 2030 (15 juta). Pengurangan jumlah petani ini dapat berlangsung bila pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan penyalurannya direncanakan dan dipersiapkan dengan baik.
4. Menetapkan kebijakan yang dapat membuat harga produk pertanian di dalam negeri cukup baik, antara lain melalui tarif bea masuk, agar diperoleh rangsangan untuk peningkatan produksi. Arah kebijakan pertanian pada umumnya seharusnyalah mensejahterakan petani.
5. Menetapkan sasaran untuk dapat kembali berswasembasa beras di tahun 2006, daging sapi di tahun 2010 dan susu sapi tahun 2015.
6. Menetapkan sasaran untuk menjadi negara nett exportir pangan di tahun 2010, dengan idopsi teknologi.
7. Mengembangkan industri pertanian dan pangan yang berkwalitas tinggi, Membangun agro industri di desa.
8. Mengembangkan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal.
Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan, dengan harapan semoga bermanfaat baqi pembangunan bangsa dan negara kita, khususnya dalam membangun kemandirian di bidang pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangar agroindustri yang memiliki daya saing yang tinggi.***
Oleh: Ir. Siswono Yudho Husodo -- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
Disampaikan pada: Seminar “Kemandirian Ekonomi Nasional” diselenggarakan oleh Fraksi Utusan Golongan Jakarta, 22 November 2002
DAFTAR PUSTAKA :
1. “Sensus Pertanian 1993”, Jakarta : BPS, 1995
2. Tomich, Thomas P dan kawan-kawan, “Transforming Agrarian Economics: Opportunities Seized, Opportunities Missed”, Ithaca : Cornell University Press,1995
3. Mantra, Ida Bagus, “Mobilitas Penduduk Sekuler dari Desa ke Kota”, Yogyakarta Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1995
4. Faturochman, Marcelinus Malo “Kemiskinan dan Kependudukan di Pedesaan Jawa”, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1995
5. Djojohadikusumo, Sumitro, “Pembangunan Ekonomi Indonesia”, Jakarta : Sinar Agape Press, 1995
6. Sayogyo, “Demokrasi dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia”, Jakarta Gramedia Widiasarana, 1996
7. Soegijoko, Sugiyanto, “Bunga Rampai Pembangunan di Indonesia” Jakarta Gramedia, 1997
8. Press Release FAO No. 00/43
9. Kliping koran HKTI berita-berita pertanian 1999, 2000, 2001, 2002 Read More..
Senin, 19 April 2010
Langganan:
Postingan (Atom)








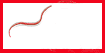









 Forex Quotes
Forex Quotes